PROSPEK DEMOKRASI DI MYANMAR
M. Adian Firnas
yanmar adalah sebuah negara yang saat ini masih dikuasai
oleh rezim militer yang otoriter. Sudah 40 tahun kelompok militer menguasai
kehidupan politik, sosial, dan ekonomi rakyat Myanmar. Sejak Jenderal Ne
Win sampai Jenderal Than Shwe rezim militer menjalankan kebijakan yang
sama yakni memberangus nilai-nilai demokrasi dan menggantikannya
dengan tatanan yang bersifat sentralistik dan otoriter.
Setiap gerakan demokrasi yang muncul sudah pasti mendapat
perlawanan dari rezim yang berkuasa. Secara sistematis rezim militer
mampu
melemahkan
berbagai
gerakan
oposisi
yang
muncul
dalam
bukunya
The
Third
dari
masyarakat sipil.
Samuel
P.
Huntington,
Wave:
Democratization in the Late Twentienth Century (1991) mencatat tahun 1974
hingga 1990-an sebagai gelombang ketiga demokrasi dunia. Huntington
melihat peristiwa kudeta oleh sekelompok perwira muda dalam gerakan
Movimento das Forcas Armadas (MFA) di Portugal yang berhasil
menggulingkan diktator Marcello Caetano sebagai awal periode gerakan ke
arah demokrasi di seluruh dunia yang kemudian dikenal sebagai gelombang
ketiga demokratisasi dunia (Huntington, 1991: 4 ).
Gerakan menuju demokratisasi di Portugal tahun 1974 tersebut
kemudian juga diikuti oleh serangkaian gerakan demokrasi di berbagai
belahan dunia. Selama 15 tahun berikutnya, gelombang demokratisasi ini
berlingkup global di mana sekitar 30 negara telah bergeser dari otoriterisme
menjadi demokrasi dan sekurangnya 20 negara lain telah dipengaruhi oleh
gelombang demokratisasi ini. Kasus Korea Selatan, Thailand, Philipina, dan
bahkan Indonesia dapat dijadikan contoh bagaimana tumbangnya rezim
otoriter di belahan dunia ketiga.
Jurnal Universitas Paramadina Vol.2 No. 2, Januari 2003: 128-141
�M. Adian Firnas
“Prospek Demokrasi di Myanmar”
Rasa optimisme yang cukup kental menyebar pada berbagai
kalangan pengamat politik internasional mengenai cerahnya prospek
demokratisasi di dunia. Tumbangnya Uni Soviet dan para penguasa totaliter
di Eropa Timur pada awal tahun 1990-an meyakinkan para pengamat bahwa
gelombang demokratisasi yang melanda seluruh belahan dunia sebagai
sesuatu yang tidak dapat mungkin dibendung.
Optimisme terhadap masa depan demokratisasi di dunia ternyata
tidak berjalan mulus dan berubah menjadi rasa pesimis ketika ternyata
beberapa negara mengalami kegagalan demokrasi, khususnya yang
dilakukan oleh kelompok militer. Salah satu dari negara tersebut adalah
Myanmar yang dikaji secara mendalam dalam tulisan ini.
Sebagai negara yang masih dikuasai rezim militer, bukan berarti
tidak ada gerakan demokrasi di negara ini. Seberapa pun derasnya arus
demokrasi melanda negara ini, pemerintahan militer yang berkuasa semakin
keras pula membendung gerakan itu, contohnya adalah penolakan militer
terhadap hasil pemilu tahun 1990 yang menempatkan Aung San Suu Kyi
bersama partainya National Leaque for Democratic (NLD) sebagai
pemenang. Berkuasanya kembali pemerintahan militer pada tahun 1990 ini
bukanlah merupakan hal yang “baru”, karena sesungguhnya ia merupakan
kelanjutan dari pemerintahan militer sebelumnya yang telah berkuasa sejak
tahun 1962.
Intervensi Militer ke dalam Sistem Politik Myanmar
Ketika Myanmar merdeka pada tahun 1948 (waktu itu bernama
Burma), di bawah pemerintahan sipil U Nu, ia mencoba menjalankan
pemerintahan yang demokratis dengan menerapkan sistem parlementer.
Sebagaimana halnya negara yang baru merdeka, pemerintahan U Nu juga
dihadapkan pada keadaan sosio-politik yang rumit. Dengan strategi
pembangunan Pydawtha (negara yang makmur), U Nu berusaha keras
menyelesaikan berbagai persoalan dalam negerinya. Strategi tersebut pada
akhirnya gagal mengatasi berbagai persoalan kompleks yang muncul, baik
129
�Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 2 No. 2, Januari 2003: 128-141
yang berkenaan dengan aspek perekonomian, pembelotan, maupun
pemberontakan (Steinberg, 1982 : 45).
Keterlibatan militer dimulai ketika Jenderal Ne Win ditugaskan untuk
mengendalikan ketertiban dan mempersiapkan pemilu 1960. Pemerintahan
militer, saat itu, berhasil memulihkan keadaan dalam negeri sampai
terselenggaranya pemilu tahun 1960 yang dimenangkan oleh U Nu dan
partainya, Union Party. Pihak militer kemudian mengultimatum pemerintah
sipil dengan memberikan waktu selama 2 tahun untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang dihadapi Myanmar. Karena pemerintah
sipil tidak dapat menata kembali kondisi dalam negeri Myanmar, yang
semakin diperparah dengan kegagalan U Nu dalam menata sistem
perekonomian dan administrasi Myanmar, maka timbul ketidakpuasan di
kalangan pro-militer dan militer. Akhirnya pada tanggal 2 Maret 1962, militer
melakukan kudeta di bawah pimpinan Jenderal Ne Win.
Keberhasilan kudeta atas PM U Nu pada tahun 1962 itu bisa
dikatakan sebagai awal keruntuhan demokrasi di Myanmar. Selama masa
pemerintahannya (1962-1988) Ne Win hanya mengakui satu partai politik,
yaitu Burmese Socialist Program Party (BSPP) yang dibentuknya sendiri.
BSPP atau yang lebih dikenal dengan Partai Lenzin ini bisa dikatakan
sebagai partai tunggal yang dilaksanakan untuk mendukung program sosialis
dengan mayoritas anggota berasal dari golongan militer. Sejak berdiri tahun
1962 dan disahkan tahun 1964 keanggotaan partai ini didominasi oleh
militer. Pada tahun 1972 militer menjadi pilar pokok dari partai (Taylor, 1980
: 40).
Keterlibatan
militer
dalam
penggagalan
demokrasi
kembali
dilakukan pada tahun 1990. Ketika itu Jenderal Saw Maung membatalkan
hasil pemilu 27 Mei 1990 yang menempatkan National Leaque for
Democration (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi sebagai pemenang pemilu.
Sampai saat ini, di bawah Jenderal Than Shwe, militer sangat kuat
mengendalikan kehidupan politik, sosial,
dan ekonomi rakyat Myanmar.
Begitu kuatnya peran militer sehingga David I. Steinberg menempatkan
130
�M. Adian Firnas
“Prospek Demokrasi di Myanmar”
Myanmar sebagai “The most monolithically military-controlled in the world”
(Neher, 1995:121)
Pilihan Kebijakan
Menurut Huntington, ketika militer melakukan kudeta terhadap
pemerintah sipil maka kemudian pemerintah militer harus memilih antara
mempertahankan kekuasaan atau mengembalikannya kepada politisi sipil;
dan antara memperluas partisipasi politik kelompok-kelompok masyarakat
atau membatasinya (Huntington, 1968: 233-237), dengan demikian,
pimpinan rezim militer dihadapkan pada 4 pilihan :
∗ Mempertahankan kekuasaan dan membatasi partisipasi;
∗ Mempertahankan kekuasaan dan memperluas partisipasi;
∗ Mengembalikan kekuasaan dan membatasi partisipasi; dan
∗ Mengembalikan kekuasaan dan memperluas partisipasi.
Dalam kasus Myanmar, untuk melihat kebijakan mana yang diambil
oleh rezim militer tidaklah susah. Dengan melihat kebijakan yang diterapkan
rezim militer pimpinan Jenderal Ne Win (1962-1988) dan rezim militer
pimpinan Jenderal Saw Maung pasca 1988 kita dapat melihat dengan jelas
bahwa rezim tersebut memilih kebijakan mempertahankan kekuasaan dan
membatasi partisipasi.
Pada masa Ne Win misalnya, segera setelah ia melakukan kudeta
atas pemerintahan sipil pimpinan Perdana Menteri U Nu tahun 1962, ia
mendirikan pemerintahan otoriter dan memerintah dengan gaya diktator
(Steinberg, 1982: 33-35). Rakyat tidak diperkenankan untuk memilih
pimpinannya sendiri, karena keputusan politik harus melalui pimpinan militer
di Rangoon. Burmese Socialist Program Party (BSPP), pimpinan jenderal Ne
Win, menjadi satu-satunya partai resmi yang berdiri. Oposisi datang dari
penjuru perkotaan dan pedalaman, tetapi selalu gagal karena pihak oposisi
tidak memiliki pemimpin kharismatik dan lemahnya masyarakat sipil
Myanmar.
131
�Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 2 No. 2, Januari 2003: 128-141
Ketika Myanmar di bawah pemerintahan militer pimpinan Jenderal
Saw Maung mengambil alih kekuasaan pada 18 September 1988
(Sulistiyanto, 1993: 78), watak otoriterisme pendahulunya diwarisi oleh
pemerintahan ini. Kudeta tahun 1988 ini dalam kenyataannya tidak dapat
diartikan sebagai adanya pergantian kekuasaan di Myanmar. Hal ini sematamata pergantian pemerintahan militer yang “lama” menjadi pemerintahan
militer yang “baru”, dari BSPP menjadi The State Law and Order Restoration
Council (SLORC). Pada dasarnya kekuasaan pemerintahanan tetap berada
di tangan militer. Sebagaimana pendahulunya, pemerintahan militer
Jenderal Saw Maung juga memimpin negara dengan otoriter. Banyak bukti
menunjukkan hal itu, misalnya penolakan SLORC terhadap hasil pemilu
tanggal 27 Mei 1990. Seperti diketahui pada pemilu ini partai NLD berhasil
merebut 392 dari 485 kursi di parlemen nasional. Hasil ini sesungguhnya di
luar prediksi militer. Sebelumnya SLORC merasa yakin bahwa partai
pemerintah, National Unity Party (NUP), akan memenangkan pemilu. Di
sinilah sifat otoriter militer muncul. Berbagai protes rakyat dihadapi dengan
tindakan represif oleh militer. Di penghujung tahun 1991 SLORC mulai
melancarkan kampanye intensif untuk menghancurkan kekuatan oposisi di
wilayah perkotaan maupun di kalangan etnis minoritas. Praktis tindakan
SLORC ini semakin melemahkan posisi sipil dalam kancah perpolitikan di
Myanmar.
Sampai saat ini, di
bawah pemerintahan Jenderal Than Shwe,
meskipun SLORC diganti menjadi The State Peace Development Council
(SPDC), pada kenyataannya lembaga ini tetap menjalankan fungsi-fungsi
lembaga sebelumnya yaitu mengontrol kehidupan sosial politik rakyat
Myanmar.
Berdasarkan uraian tadi sampailah pada pertanyaan mengapa rezim
militer Myanmar menerapkan kebijakan mempertahankan kekuasaan dan
membatasi partisipasi politik sipil? Untuk menjawab pertanyaan tersebut
penulis menggunakan kerangka berpikir yang dikemukakan oleh Ulf
Sundhaussen tentang penarikan diri militer dari pemerintahan (Prisma No.7,
132
�M. Adian Firnas
“Prospek Demokrasi di Myanmar”
1995: 60-65). Menurut Sundhaussen, untuk menentukan keputusan mana
yang hendak dipakai tidak bisa hanya tergantung pada kecenderungan atau
kemauan bebas dari pimpinan. Sundhaussen kemudian mengembangkan
dalil Finer bahwa keberhasilan intervensi militer tergantung pada faktor
internal dan eksternal yang sesuai, yang mencakup tidak hanya masuknya
militer ke dalam politik tetapi juga keluarnya militer dari dalam politik. Maka,
memilih di antara pilihan yang ada juga tergantung pada faktor internal dan
faktor eksternal militer yang sesuai, mencakup tidak hanya masuknya militer
ke dalam politik tetapi juga keluarnya militer dari dalam politik, maka
memilih di antara pilihan yang ada juga tergantung pada faktor internal dan
faktor eksternal militer. Sundhaussen kemudian membuat alat analisis
dengan mengelompokkan variabel-variabel internal dan eksternal ini ke
dalam “alasan” dan “prasyarat”.
Alasan Militer Menarik Diri
Ada tiga daftar perangkat alasan militer menarik diri dari tanggungjawab pemerintahan seperti yang ditawarkan berikut ini. Pertama, faktor
eksternal
militer,
yaitu
adanya
oposisi
terhadap
keberlangsungan
kekuasaannya. Oposisi mungkin berbentuk protes menentang penindasan
dan korupsi dan/atau karena rezim tidak mampu menyelesaikan setiap krisis
secara efektif sebagaimana janji semula. Kedua, adanya alasan eksternal
terhadap negara. Rezim militer yang secara ekonomi, militer, dan logistik
tergantung kepada negara lain dapat terancam bila donatur mereka menarik
dukungannya. Ketiga, penarikan diri adalah faktor internal militer. Pimpinan
rezim akan bersedia menarik diri karena percaya bahwa tatanan demokrasi
yang tetap memasukkan prinsip supremasi sipil atas militer pada dasarnya
sangat diperlukan.
Prasyarat bagi Penarikan Diri Militer
Bila rezim militer masih berada dalam posisi pembuat keputusan,
mereka juga akan mempertimbangkan prasyarat-prasyarat bagi penyerahan
133
�Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 2 No. 2, Januari 2003: 128-141
kekuasaan. Sundhaussen kemudian membuat daftar tiga prasyarat bagi
penarikan diri militer. Pertama, yang merupakan prasyarat mutlak, adalah
seluruh pengelompokan di dalam tubuh militer yang mampu melakukan aksi
politik secara sepihak sepakat menyerahkan kekuasaan. Bila konsensus
demikian tidak tercapai, faksi militer tertentu mungkin akan merebut
kekuasaan dari pimpinan rezim yang bermaksud melepaskan diri dari politik,
atau mungkin melakukan intervensi
pemerintahan
sipil.
Kedua,
kembali
setelah masa singkat
kepentingan-kepentingan
yang
dianggap
pimpinan rezim militer sebagai hal esensial harus terjamin. Dapat dipahami
mereka sangat enggan menyerahkan kekuasaan bila hal ini berarti
membuka diri mereka terhadap kemarahan lawan politiknya. Karena itu
harus dirancang prosedur untuk melindungi secara fisik keselamatan
pimpinan rezim militer. Kemudian rezim sipil pengganti harus, setidaknya
untuk beberapa waktu, menghindari pemotongan anggaran pertahanan
secara drastis bila hal ini dapat menyebabkan memburuknya kondisi
pelayanan atau mengurangi jumlah angkatan bersenjata. Kelompok sipil
harus memperhitungkan pula apa yang dinilai militer sebagai kepentingan
nasional. Rezim militer tidak akan menyerahkan kekuasaan secara sukarela
bila mereka yakin landasan ideologi bangsa akan diperkosa oleh pengganti
sipil mereka.
Ketiga, adalah tersedianya apa yang dipandang pimpinan militer
sebagai alternatif politik yang dapat terus bertahan. Rezim militer harus
diyakinkan bahwa keberadaan elite-elite tidak hanya menyiapkan jaminan
bagi kepentingan pribadi dan kelompok mereka, tetapi juga harus mampu
menciptakan pemerintahan yang stabil, agar mereka bersedia menyerahkan
kekuasaan.
Penentuan Pilihan Kebijakan
Pimpinan rezim militer, dalam memutuskan salah satu dari keempat
pilihan seperti yang disebutkan Huntington di atas, akan tergantung pada
konstelasi alasan dan prasyarat yang ada. Artinya, alasan maupun prasyarat
134
�M. Adian Firnas
“Prospek Demokrasi di Myanmar”
menjadi penting dalam pilihan kebijakan; walaupun tidak semuanya memiliki
urutan preferensi yang sederajat. Beberapa variabel barangkali tidak
berlaku, sementara variabel lainnya mungkin mendominasi pertimbangan
(Sundhaussen, 1995: 63).
Sebagai perbandingan, untuk lebih memperjelas konsep yang telah
dikemukakan Sundhaussen di atas, kasus tumbangnya berbagai rezim
otoriter di Amerika Latin atau Portugal yang disebut-sebut sebagai pemicu
gerakan demokratisasi ketiga dapat dijadikan contoh.
Persoalan eksternal militer misalnya, seperti oposisi terhadap rezim,
dengan menggunakan kasus Venezuela, terbukti mampu mendesak rezim
tersebut untuk segera menjalankan demokrasi. Perlawanan dan protes
terbuka yang dilakukan oleh Accion Democratica dan partai-partai politik lain
terhadap Jenderal Perez Jiminez telah berhasil membawa negara itu menuju
proses redemokratisasi kembali pada tahun 1958 (Karl, 1993: 300). Rezim
militer yang secara ekonomis, militer, dan logistik tergantung kepada negara
lain dapat terancam bila donatur mereka menarik dukungannya. Kebijakan
hak-hak asasi manusia (HAM) yang dilontarkan pemerintah Amerika Serikat
tentu mempunyai dampak terhadap rezim pemerintahan otoriter di Amerika
Latin (Sundhaussen, 1995: 61).
Kasus Brasil, Cile, dan Argentina dapat juga dijadikan contoh untuk
melihat persoalan internal yang menyangkut jaminan terhadap kepentingan
militer. Menurut Stepan (1996: 87) setidaknya ada dua kepentingan
kelembagaan utama yang ingin pemerintahan militer lindungi jika mereka
mengundurkan diri dari kekuasaan langsung. Dalam setiap pidato, para
pemimpin
militer
mengingatkan
pembalasan (revanchismo)
untuk
menghadapi
terhadap mereka.
setiap
bentuk
Dengan jelas mereka
memperkirakan bahwa seorang presiden sipil akan waspada terhadap
revanchismo, dan akan menjaga keutuhan sistem keamanan negara.
Kepentingan utama lain yang ingin mereka pertahankan, dan mereka yakini
akan tetap terpenuhi di bawah pemerintahan sipil, adalah dilanjutkannya
pembangunan industri persenjataan dan jaminan terhadap anggaran belanja
135
�Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 2 No. 2, Januari 2003: 128-141
militer. Stepan juga mencatat bahwa selama rezim otoriter berkuasa di
Uruguay, Cile, dan Argentina terjadi peningkatan belanja militer yang
signifikan (lihat tabel 1).
Tabel 1. Tabel belanja militer sebagai persentase GNP di tiga rezim otoriter:
Argentina, Cile, dan Uruguay, 1972-1982 (Stepan, 1996: 105).
TAHUN
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
ARGENTINA
1,4
1,7
1,9
0,8
3,2
3,2
3,0
3,2
3,6
3,9
3,5
CILE
2,3
3,7
4,9
4,8
4,0
4,8
4,2
3,6
3,6
3,7
4,3
URUGUAY
2,4
2,4
2,4
2,7
2,4
2,7
2,3
2,9
2,9
4,0
4,1
Bila melihat peningkatan nilai belanja militer dalam tabel di atas,
nampaknya sangat masuk akal ketika militer di negara tersebut menuntut
jaminan tetap dipertahankannya kepentingan tersebut pada saat kekuasaan
beralih ke tangan sipil.
Kondisi serius juga muncul ketika oposisi radikal terhadap penguasa
militer berkembang di dalam kedinasan mereka sendiri. Kepemimpinan
rezim dapat diganti – dengan paksa bila perlu – menjadi junta baru yang
cenderung mengembalikan kekuasaan kepada sipil. Kasus Portugal
memperlihatkan bahwa aksi politik yang dilakukan oleh sekelompok perwira
muda dalam Movimento das Forcas Armadas pada tahun 1974 telah
menghancurkan rezim otoriter Marcello Caetano (Huntington, 1991: 4).
Berikutnya setelah memerintah selama satu tahun pemerintahan militer
kemudian menyerahkan kekuasaan kepada sipil.
Terakhir, agar proses peralihan kekuasaan dapat berjalan lancar,
rezim militer harus diyakinkan bahwa rezim sipil pengganti harus mampu
menciptakan pemerintahan yang stabil dan mengatasi persoalan-persoalan
136
�M. Adian Firnas
“Prospek Demokrasi di Myanmar”
mendesak yang dialami negeri itu. Kegagalan demokrasi di Bolivia pada
tahun 1980 dapat dijadikan contoh untuk menjelaskan persoalan ini. Pada
akhir tahun 1979 Bolivia menyelenggarakan pemilu yang relatif jujur. Siles
dan Paz berhasil merebut suara terbanyak dengan masing-masing
memperolah 528.700 dan 527.000 suara, sementara Jenderal Banzer hanya
memperoleh 218.000 suara (Whitehead, 1993: 70). Menurut konstitusi
Bolivia, bila tidak ada calon yang meraih lebih dari 50% suara maka
persoalan pemilihan presiden harus diserahkan ke kongres. Setelah
dibicarakan selama sembilan hari di kongres ternyata pada akhirnya
membawa kegagalan pada konsolidasi demokrasi. Baik Siles maupun Paz
justru harus mendukung calon presiden lain yang dipilih kongres. Kegagalan
konsolidasi demokrasi ini oleh militer kemudian dilihat sebagai proses yang
berbahaya bagi institusionalisasi negeri itu. Dua bulan kemudian angkatan
bersenjata
dengan
singkat
dan
berdarah
merebut
kekuasaan
dan
membubarkan kongres.
Bila melihat perkembangan di Myanmar, berdasarkan uraian di atas,
tampaknya belum terdapat alasan dan prasyarat yang dapat menyebabkan
militer harus mengevaluasi kembali perannya. Adanya oposisi dari rakyat
misalnya, meskipun setelah kudeta tahun 1988 bangkit kelompok oposisi
yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, Tin Oo, bekas tokoh mahasiswa
seperti Moe Thee Zun, Min Ko Naingn, dan lain-lain (Sulistiyanto, 1993: 80),
tetapi secara signifikan kekuatan oposisi ini tidak mampu melemahkan
militer. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, yaitu semakin melemahnya
kekuataan oposisi. Hal ini disebabkan karena pemerintahan militer selalu
menerapkan kebijakan yang represif terhadap upaya oposisi terhadap
pemerintahan militer. Dengan strategi “memecah-belah” kelompok oposisi
dan meningkatkan operasi militer anti pemberontakan, SLORC mampu
melemahkan gerakan oposisi terhadap pemerintah.
Demikian pula alasan eksternal terhadap negara. Rezim militer
Myanmar tidak mempunyai ketergantungan secara ekonomi, militer, dan
logistik terhadap negara lain. Seperti diketahui segera setelah SLORC
137
�Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 2 No. 2, Januari 2003: 128-141
menolak peralihan kekuasaan kepada NLD pada tahun 1990, tekanan dunia
internasional
terhadap Myanmar
semakin meningkat.
Misalnya saja
Masyarakat Eropa dan kongres Amerika Serikat segera membuat sanksisanksi ekonomi dan militer terhadap Myanmar. Namun karena tidak adanya
ketergantungan ekonomi, militer, dan logistik terhadap negara-negara
tersebut
maka
tekanan-tekanan
dunia
internasional
tidak
mampu
melemahkan posisi rezim militer yang berkuasa (Sulistiyanto, 1993: 82).
Yang terakhir adalah persoalan internal, yaitu kerelaan militer untuk
menyerahkan kekuasaan kepada sipil. Keadaan ini tampaknya akan sangat
sulit terjadi di Myanmar, sebab sejak awal ketika militer melakukan kudeta
terhadap pemerintahan sipil pada tahun 1962, militer Myanmar telah
menganggap dirinya sebagai kelanjutan dari tiga dinasti terdahulu yang telah
berhasil menyatukan Myanmar. Dinasti-dinasti besar tersebut adalah
Anurawtha,
Bayyinaung,
dan
Alungpaya
(Cheong,
1988:
297-298).
Pemikiran seperti inilah yang pada akhirnya dijadikan justifikasi bagi militer
untuk tetap mempertahankan kekuasaannya.
Demikian juga mengenai prasyarat bagi penarikan diri militer.
Tampaknya belum ada prasyarat yang memungkinkan militer Myanmar
menyerahkan kekuasaan kepada sipil. Pemerintahan militer era SLORC ini
dikenal sangat solid, sehingga pemerintahan ini dijuluki juga dengan
pemerintahan junta militer. Yang tidak kalah penting adalah sulitnya
menemukan elite-elite sipil yang secara potensial berfungsi sebagai
alternatif politik penguasa militer. Oposisi yang terjadi di Myanmar, seperti
menawarkan program dan derajat stabilitas yang layak, merupakan
signifikasi
krusial
bagi
prospek
pensipilan
kembali
pemerintahan
(Sundhaussen, 1995: 65). Inilah yang sampai saat ini masih dilakukan oleh
militer Myanmar.
Dalam perspektif yang lain, di belahan dunia ketiga terlihat “bebas
dari kelaparan” memperoleh prioritas lebih tinggi daripada hak-hak sipil.
Oleh karena itu pemerintah yang kuat, termasuk rezim militer seringkali
dianggap sebagai penyelesaian yang tepat dari kesulitan ekonomi.
138
�M. Adian Firnas
“Prospek Demokrasi di Myanmar”
Keberhasilan militer mengatasi persoalan ekonomi yang terjadi di Myanmar
pada tahun 1988, meskipun pada tahap yang minimal, dijadikan legitimasi
bagi militer untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Reformasi ekonomi
yang dijalankan oleh militer pada tahun 1989 telah membawa perubahan
dan peningkatan yang signifikan terhadap devisa negara. Hingga Juni 1989,
SLORC menerima peningkatan cadangan devisa yang berlipat ganda yaitu
sekitar US $ 150 juta, dibanding US $ 28 juta sebelum Maret 1989 dan
sekitar US $ 10 juta pada saat terjadinya kudeta militer pada bulan
September 1988. Hal ini meningkatkan juga keikutsertaan perusahaanperusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor, yakni mencapai
sekitar 1.200 perusahaan yang tercatat hingga Januari 1990. Sampai tahun
1995 tercatat jumlah nilai investasi asing berturut-turut sebagai berikut:
Inggris US $ 643 juta, Singapura US $ 604 juta, Perancis US $ 455 juta,
Thailand US $ 444 juta, Amerika Serikat US$ 241 juta, Malaysia US $ 227
juta, dan Jepang US $ 106 juta (FEER, 15/08/96).
Demikianlah, untuk memahami pemerintahan militer Myanmar tidak
semua variabel yang ditawarkan oleh Sundhaussen dapat diterapkan.
Dengan melihat perbandingan Amerika Latin dan Portugal, rezim otoriter
Myanmar mempunyai keunikan sendiri yang justru membuat rezim itu
semakin kokoh, yaitu kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya
sendiri tanpa tergantung dari negara lain. Ide sosialisme, seperti bebas dari
kelaparan, yang setidaknya berhasil dicapai oleh rezim tersebut dijadikan
justifikasi bagi kelangsungan rezimnya.
Kesimpulan
Dengan
memperhatikan
uraian
di
atas
nampaknya
proses
perkembangan negara Myanmar menuju sebuah negara yang demokratis
relatif berjalan stagnan setelah negara tersebut dikuasai oleh rezim militer.
Tanda-tanda kehidupan demokrasi di negara ini semakin tenggelam dengan
adanya keinginan yang kuat dari pihak militer untuk tetap mempertahankan
dan memperkuat kekuasaannya di negara tersebut.
139
�Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 2 No. 2, Januari 2003: 128-141
Nampaknya dibutuhkan peranan besar dari komunitas internasional
untuk memberikan spirit terhadap setiap gerakan demokrasi yang terjadi.
Tekanan secara simultan harus terus dilakukan terhadap rezim yang
berkuasa untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan meninggalkan
watak otoriterisme yang terbukti semakin tidak populer dalam era globalisasi
ini.
140
�M. Adian Firnas
“Prospek Demokrasi di Myanmar”
Daftar Pustaka
Cheong, Young Mun. 1988. Soldier and Stability in Southeast Asia. Singapura:
ISEAS.
Finer, S.E. 1962. The Man on Horseback. London: Pall Mall.
Huntington, Samuel P. 1968. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale
University Press.
Huntington, Samuel P. 1991. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth
Century. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
Janowitz, Morris. 1992. The Military in the Political Development. New York: Paragon
House.
Maung Mya. 1992. Totalitarian in Burma: Prospect for Economic Development. New
York: Paragon House.
Neher, Clarck D. 1995. Democracy and Development in Southeast Asia. Colorado:
Westview Press.
Steinberg, I. David. 1982. Burma: a Socialist Nation of Southeast Asia. Colorado:
Westview Press.
Stepan, Alfred. 1997. Militer dan Demokratisasi. Jakarta: Pustaka Grafiti.
Sulistiyanto, Priyambudi. 1993. Revolusi yang Tertunda. Prisma No. 6. Jakarta.
Sundhaussen, Ulf. 1995. Indonesia's New Order: A Model for Myanmar? Asian
Survey, Vol. XXXV, No.8, August 1995.
Taylor, Robert H. 1980. Burma, dalam Harold Crouch “Military Civilian Relation in
Southeast Asia”. Singapore: Koon Wah Printing.
Whitehead, Laurence. 1993. Demokrasi Bolivia yang Gagal 1977-1980, dalam
Gilermo O’Donnel “Transisi menuju Demokrasi: Kasus Amerika Latin”.
Jakarta: LP3ES.
141
�
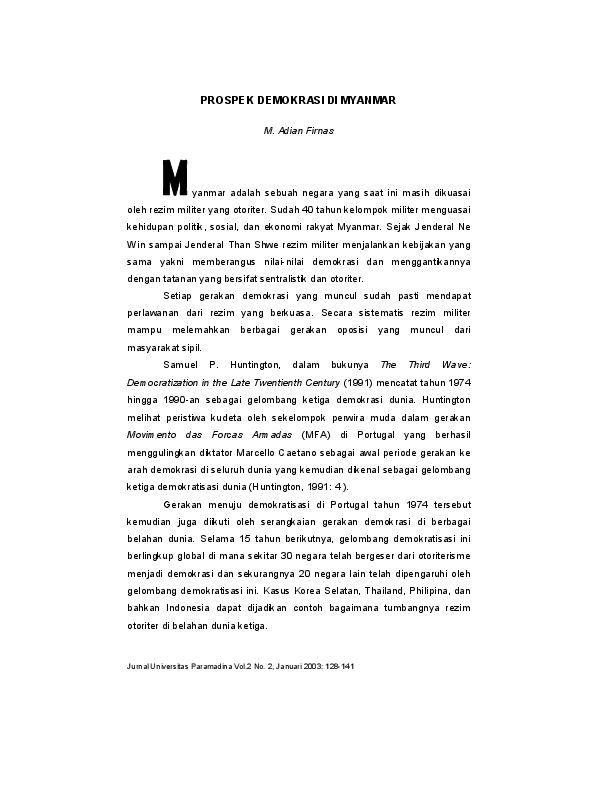
 Doddy Yasman
Doddy Yasman