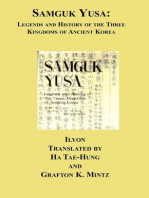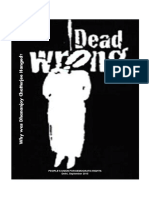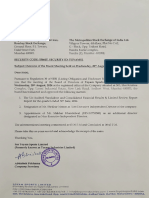Ketika Pangeran Minta Jabatan: Kajian Filologis Terhadap Sepucuk Surat Untuk Raffles (1811)
Ketika Pangeran Minta Jabatan: Kajian Filologis Terhadap Sepucuk Surat Untuk Raffles (1811)
Uploaded by
Yadi KartonoCopyright:
Available Formats
Ketika Pangeran Minta Jabatan: Kajian Filologis Terhadap Sepucuk Surat Untuk Raffles (1811)
Ketika Pangeran Minta Jabatan: Kajian Filologis Terhadap Sepucuk Surat Untuk Raffles (1811)
Uploaded by
Yadi KartonoOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Copyright:
Available Formats
Ketika Pangeran Minta Jabatan: Kajian Filologis Terhadap Sepucuk Surat Untuk Raffles (1811)
Ketika Pangeran Minta Jabatan: Kajian Filologis Terhadap Sepucuk Surat Untuk Raffles (1811)
Uploaded by
Yadi KartonoCopyright:
Available Formats
P- ISSN 2087-1074 E- ISSN 2685 -7391
DOI: 10.37014/jumantara.v12i2.1248
Diajukan 28-10-2020 Direview 28-11-2020 Direvisi 13-04-2021 Diterima 19-05-2021
KETIKA PANGERAN MINTA JABATAN:
KAJIAN FILOLOGIS TERHADAP SEPUCUK SURAT
UNTUK RAFFLES (1811)
Hazmirullah Aminuddin
Peneliti Mandiri
Korespondensi: azmeer125@gmail.com
ABSTRACT
In this article, I discuss a letter from three high-ranking officials of the Cirebon Sultanate to Thomas Stamford
Raffles. The letter written on 25 Syaban 1226 AH (September 11, 1811 AD) is a collection of the National
Archives of the Republic of Indonesia and is coded ID-ANRI K66a, File 3584, Folio 683. Through the letter,
they the letter, in essence, they asked for a position to Raffles. As the “old people” in the Cirebon Sultanate, they
felt worthy and could occupy certain positions which they submitted themselves to Raffles. In this article, the
letter firstly was studied by using the philology theory that contains the method of manuscript study (codicology)
and the method of text study (textology). Furthermore, the manuscript content was dialogued to the historical
fact in the Cirebon Sultanate, especially in the context of the British plan to occupy Java, so that we obtained a
complete understanding of the context of writing the letter. The result shows that when the letter was written, the
British had not fully controlled Java. The three high-ranking officials of the Cirebon Sultanate only took
advantage of the situation because they knew that power in Java would soon transfer to the British hands.
However, until the end of the British interregnum period in 1816, there is no evidence that the request was
granted by Raffles.
Keywords: Manuscript; Cirebon; Pangeran Arya Kidul; Raffles; the Conquest of Java.
ABSTRAK
Di dalam artikel ini, penulis mengkaji sepucuk surat yang ditulis oleh tiga petinggi Kesultanan Cirebon kepada
Thomas Stamford Raffles pada tanggal 25 Syaban 1226 H (11 September 1811 M). Naskah tersebut merupakan
koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia dan diberi kode ID-ANRI K66a, File 3584, Folio 683. Melalui surat
itu, pada intinya, mereka meminta jabatan kepada Raffles. Sebagai “orang lama” di Kesultanan Cirebon, mereka
merasa layak dan memiliki kemampuan untuk menduduki beberapa jabatan tertentu yang mereka ajukan kepada
Raffles. Di dalam artikel ini, naskah tersebut terlebih dahulu dikaji menggunakan teori filologi yang di dalamnya
terdapat metode kajian naskah (kodikologi) dan metode kajian teks (tekstologi). Selanjutnya, kandungan naskah
didialogkan dengan fakta sejarah di Kesultanan Cirebon, terutama dalam konteks rencana Inggris untuk
menduduki pulau Jawa. Dengan demikian, diperoleh pemahaman utuh mengenai konteks kehadiran naskah surat
tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika surat itu ditulis, Inggris belum sepenuhnya menguasai
pulau Jawa. Para penulis surat hanya memanfaatkan situasi karena menyadari bahwa tak lama lagi kekuasaan
atas tanah Jawa akan berpindah tangan. Meskipun demikian, hingga masa pemerintahan peralihan Inggris
berakhir pada 1816, tidak ada bukti bahwa permintaan mereka dikabulkan oleh Raffles.
Kata Kunci: Manuskrip; Cirebon; Pangeran Arya Kidul; Raffles; Penaklukan Jawa.
1. PENDAHULUAN
Pada pertengahan bulan Januari 2021 lalu, salah seorang guru besar di Universitas Sumatera
Utara jadi perbincangan ramai orang di media sosial setelah ia mengunggah foto surat lamaran yang
ditujukan kepada Presiden Joko Widodo1. Melalui akun Twitter, ia mengunggah empat foto, yakni
amplop surat, dua lembar surat lamaran, dan curriculum vitae. Sang guru besar memulai surat lamaran
dengan memperkenalkan diri sebagai pendukung setia Presiden Jokowi sejak periode pemerintahan
pertama (2014-2019), dilengkapi dengan tangkapan layar cuitan di Twitter. Selanjutnya, ia
menyinggung penangkapan dua anggota Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Kelautan dan
Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Ia pun menyertakan tangkapan
layar cuitannya di akun Twitter, “Yth. Pak @Jokowi, cukup dua menteri sudah korban akibat
1
Ibnu Hariyanto. 2021. "Pengakuan Guru Besar USU Prof Henuk Lamar Jabatan Menteri Jokowi Via Surat",
Diakses pada 27 Januari 2021, https://news.detik.com/berita/d-5337432/pengakuan-guru-besar-usu-prof-
henuk-lamar-jabatan-menteri-jokowi-via-surat.
Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara Vol. 12 No. 2 Tahun 2021 183
Hazmirullah Aminuddin
keserakahan mereka jadi wajar ditangkap @KPK_RI. Saatnya Pak @Jokowi selektif pilih pembantu
jangan karena usulan/desakan dari parpol pengusung, tapi manfaatkan mereka setia mendukung di
medsos, misalnya tak dilabeli buzzerRp”. Di lembar berikutnya, sang guru besar secara terus terang
meminta jabatan kepada Presiden Jokowi. Ia menulis, “Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya
mengirim berkas-berkas lama yang pernah saya kirimkan ke Bapak Presiden Jokowi di masa lalu
guna sekiranya dapat dipertimbangkan kembali agar saya ditempatkan di posisi mana saja sesuai
kompetensi saya (lihat Biography, terlampir) jika dalam waktu dekat ada pergantian dua menteri
yang tertangkap tangan oleh KPK”.
Ternyata, guru besar di Universitas Sumatera Utara itu bukanlah orang pertama yang berlaku
demikian. Soalnya, pada tahun 1811, tiga petinggi di Kesultanan Cirebon juga melakukan hal serupa.
Mereka adalah Pangeran Arya Kidul, Pangeran Raja Kartaningrat, dan Imam Kadi. Memanfaatkan
situasi yang tengah berlangsung di Jawa, mereka berkirim surat dan secara to the point meminta
jabatan kepada Thomas Stamford Raffles. Informasi tersebut termaktub di dalam sepucuk surat yang
ditulis pada tanggal 22 Syaban 1226 H atau bertepatan dengan 11 September 1811 M, kini dikoleksi
oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, dan diberi kode ID-ANRI K66a, File 3584, Folio 683.
Padahal, kalakian, proses penaklukan Jawa belum sepenuhnya rampung. Gubernur Jenderal Prancis-
Belanda (Franco-Dutch) di Hindia Timur Jan Willem Janssens belum lagi tertangkap dan, dengan
demikian, Raffles belum pula menduduki jabatan sebagai Letnan Gubernur Jawa dan wilayah
taklukannya (Lieutenant Governor Java and Its Dependencies).
Secara sepintas lalu, surat tersebut bersifat pribadi sehingga bisa jadi dianggap tidak ada artinya.
Akan tetapi, ternyata, di dalam surat itu, terdapat sejumlah informasi penting yang layak untuk
dianalisis secara mendalam. Kepada Raffles, para penulis surat menyatakan bahwa mereka merupakan
“orang-orang lama” di Kesultanan Cirebon sehingga merasa layak dan berkemampuan untuk
menduduki jabatan tertentu. Mereka juga menggunakan istilah “pétor” untuk menyebut pejabat
kolonial setingkat residen yang ditugaskan di Cirebon. Di dalam surat itu, diungkapkan pula wilayah
tugas Pétor Cirebon mencakup pusat Kesultanan Cirebon dan tujuh daerah di sekitar Cirebon hingga
ke Tanah Galuh. Uniknya, mereka menulis sebagian daerah itu dengan sebutan lama. Satu hal lagi,
pada saat membaca kolofon, penulis menemukan kenyataan bahwa mereka tidak menulis surat dari
Cirebon, tetapi dari Batavia. Mengapa demikian? Inilah ruang lingkup yang akan disajikan di dalam
artikel ini. Menurut penulis, penelitian terhadap naskah surat ini penting dilakukan. Pasalnya, kini, tak
semua kalangan mampu membaca--apalagi memahami kandungan--teks yang ditulis dengan
menggunakan aksara Jawi (bahasa Melayu), termasuk surat yang menjadi objek penelitian ini.
Meskipun demikian, tentu saja, penelitian tak boleh dilakukan terhadap fisik naskah semata, tetapi
juga kandungan teks dan konteks yang melatarbelakangi kehadirannya.
2. METODE
Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu menggunakan metode penelitian filologi yang di
dalamnya terdapat metode kajian naskah (kodikologi) dan metode kajian teks (tekstologi). Kodikologi
dimaksudkan untuk memperoleh lalu mendedahkan informasi ihwal seluk-beluk naskah, seperti aksara,
bahasa, bahan, usia, tempat penulisan, penyalin, dan perkiraan penulis naskah (Baried et al. 1985, 55).
Sementara dalam tekstologi, penulis memilih untuk menggunakan metode edisi standar/kritis, satu dari
dua pilihan untuk penyajian naskah tunggal. Selanjutnya, penulis menyertakan hasil transformasi teks
surat tersebut. Menurut Fathurahman (2015, 95-96), teks yang ditulis dalam bahasa Melayu tidak
diterjemahkan meski terdapat kata arkais dan kini tidak lagi digunakan. Hal itu lantaran teks berbahasa
Melayu pada dasarnya memiliki struktur yang identik dengan bahasa Indonesia. Terkait dengan kata-
kata yang dianggap arkais, itu dapat dijelaskan tersendiri dalam catatan kaki. Sementara itu, dalam
konteks penelitian ini, transformasi yang dimaksud berada dalam ranah linguistik, yakni “mengubah
struktur gramatikal (suatu bahasa) menjadi struktur gramatikal (bahasa) lain disertai dengan
184 Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara Vol. 12 No. 2 Tahun 2021
Ketika Pangeran Minta Jabatan: Kajian Filologis terhadap Sepucuk Surat untuk Raffles (1811)
menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya” 2 . Langkah ini dimaksudkan untuk
meminimalkan ketaksaan (ambiguitas) yang sangat mungkin dihadapi oleh para pembaca masa kini.
Hal itu mengingat tidak semua pembaca memahami struktur bahasa Melayu. Arkian, teks yang
terdapat di dalam naskah tersebut didialogkan dengan fakta sejarah, terutama terkait dengan
Kesultanan Cirebon pada masa pemerintahan Sultan Sepuh VII (1791-1816) dan rencana ekspedisi
Inggris untuk menduduki Jawa hingga penyerahan diri Gubernur Jenderal Prancis-Belanda Jan Willem
Janssens, yakni pada rentang tahun 1810-1811. Hal itu dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman
utuh mengenai latar belakang dan konteks penulisan surat tersebut.
3. DESKRIPSI NASKAH
Objek penelitian ini adalah sepucuk surat koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
yang diberi kode ID-ANRI K66a, File 3584, Folio 683. Naskah itu merupakan bagian dari bundel
yang diberi judul “Arsip Gubernur-Jenderal dan Dewan Hindia (Pemerintah Agung) pada VOC
(Verenigde Oostindische Compagnie) dan para pejabat penerusnya, 1612-1812”. Bundel tersebut
memiliki volume 500 meter linier, berbahan kertas, dengan nomor inventaris 1 hingga 4.631. Surat
tersebut ditulis oleh Pangeran Arya Kidul, yang juga mengatasnamakan Pangeran Raja Kartaningrat
dan Imam Kadi Cirebon, kepada Thomas Stamford Raffles3. Informasi tersebut dapat segera diketahui
di bagian awal surat, di mana terdapat kalimat “Bahwa inilah surat tulus serta ikhlas…yaitu daripada
sahaya Pangeran Arya Kidul, dan Pangeran Raja Kartaningrat, dan Imam Kadi…disempurnakan
Allah subḥānāhū wa ta’ālā jua kiranya kepada Paduka Seri Tuan Besar… Gubernur (Jenderal)
(Raffles Esquire)”. Sementara merujuk kolofon, yang terdapat di bagian akhir surat, dinyatakan bahwa
surat tersebut ditulis di Batavia pada tanggal 22 Syaban 1226 H (bertepatan dengan 11 September
1811 M). Melalui surat itu, ketiga pejabat di Kesultanan Cirebon tersebut secara terang-terangan
meminta jabatan kepada Raffles dengan alasan bahwa mereka merupakan “orang-orang lama” yang
tahu betul seluk-beluk Cirebon. Dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi, mereka menyatakan
kesanggupan untuk menduduki jabatan, seperti “raja kepala” Negeri Cirebon, “tumenggung kepala” di
salah satu dari tujuh daerah yang berada dalam wilayah tugas Pétor Cirebon, atau penanggung jawab
urusan perdagangan di serata Cirebon.
Teks ditulis di atas selembar kertas Eropa “J Whatman 1809” berukuran folio berwarna putih
kekuning-kuningan. Naskah dalam kondisi baik dan seluruh teks masih dapat terbaca, kecuali bagian
kop surat. Teks hanya terdapat di bagian verso, diketahui karena penulis membaca tanda air
(watermark) “J Whatman 1809”, yang berorientasi atas-bawah, secara terbalik. Seperti disinggung
sebelumnya, penulis naskah membubuhkan kepala surat di bagian kiri (left-hand) atas kertas dan
terdiri atas dua baris. Akan tetapi, penulis hanya dapat membaca teks yang berada di baris kedua,
yakni “al-munawwir al-samāwāt”, sedangkan teks yang terdapat di baris pertama tidak dapat dibaca
karena sompeng. Teks di dalam surat itu terdiri atas 19 baris. Perinciannya, sebanyak 16 baris teks
ditulis dengan menggunakan aksara Jawi (bahasa Melayu) dan 3 baris teks menggunakan aksara (dan
bahasa) Jawa. Tiga baris teks yang terdapat di bagian bawah surat itu merupakan tanda persetujuan
ketiga pengirim surat, yakni Pangeran Arya Kidul, Pangeran Raja Kartaningrat, dan Imam Kadi
Cirebon.
Surat ini terdiri atas tiga bagian, yakni pembuka, isi, dan penutup (yang berisi kolofon), tetapi
tidak dipisahkan ke dalam bentuk alinea-alinea. Bagian pembuka surat dibatasi oleh sebuah perenggan
yang lazim digunakan dalam persuratan Melayu, dalam hal ini “wa ammā ba’du”. Sementara itu, isi
surat terbagi menjadi dua pokok pikiran dan dibatasi oleh kata “syahdan”. Di bagian kanan (right-
hand) atas kertas, berjarak 2 cm di atas kata pertama surat, terdapat angka Arab “683” yang ditulis
2
Kamus Besar Bahasa Indonesia (webiste). Diakses pada 27 Januari 2021, https://kbbi.web.id/transformasi.
3
Arsip Nasional Republik Indonesia (website). Diakses pada 27 Januari 2021, https://sejarah-
nusantara.anri.go.id/pagebrowser/icaatom-dasa-anri-go-id_386-ead-xml-1-
3584/#source=1&page=684&accessor=thumbnails&view=imagePane&size=857.
Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara Vol. 12 No. 2 Tahun 2021 185
Hazmirullah Aminuddin
dengan menggunakan pensil, sedangkan angka Arab “684” dituliskan di bagian sebaliknya yang tak
mengandung teks. Angka Arab inilah yang menjadi penanda identitas “folio” naskah surat tersebut.
Gambar 1. Naskah surat dari Pangeran Arya Kidul untuk Raffles tanggal 22 Syaban 1226 H
Sumber: Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (2021)
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Kekhasan Penulisan Naskah
Sebelum menyajikan edisi dan transformasi teks, penulis merasa perlu untuk terlebih dahulu
mendedahkan berbagai kekhasan yang terdapat di dalam naskah objek penelitian ini.
Kekhasan yang dimaksud adalah:
(1) Penulis surat membubuhkan frasa “…al-munawwir al-samāwāt” sebagai kepala surat.
Seperti dinyatakan di bagian sebelumnya, kepala surat sesungguhnya terdiri atas dua
baris teks. Tetapi, penulis tidak dapat membaca teks baris pertama karena kertas yang
sompeng. Sayangnya, teks kepala surat ini tidak ada dalam daftar yang dibuat oleh
Gallop (1994, 56-61) sehingga membuatnya tetap menjadi misteri. Hal itu berarti pula
bahwa frekuensi penggunaan teks kepala surat ini sangat jarang, bahkan mungkin
satu-satunya, tidak seperti Qawluhu al-ḥaqq (atau bentuknya yang lebih panjang,
Qawluhu al-ḥaqq wa kalāmuhu al-ṣidq), al-Mustaḥaqq, Yā nūr al-syams wa al-qamar
wa al-nujūm, atau Yā Qādiy al-Ḥājāt. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk
mengungkap teks lengkap kepala surat tersebut.
186 Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara Vol. 12 No. 2 Tahun 2021
Ketika Pangeran Minta Jabatan: Kajian Filologis terhadap Sepucuk Surat untuk Raffles (1811)
(2) Sebagaimana kelaziman dalam persuratan Melayu, penulis surat tidak membubuhkan
huruf kapital, tanda baca, dan paragraf. Sebagai penanda permulaan bagian baru (dan
juga tanda baca) dalam surat, digunakan beberapa kata tertentu, seperti “syahdan”
(baris ke-11), “adapun” (baris ke-8), serta kata “dan” yang berfungsi sebagai tanda
koma (baris ke-2, ke-9, dan ke-10). Khusus untuk pemerincian nama daerah,
sebagaimana terdapat di baris ke-9 dan ke-10, penulis surat tak hanya menggunakan
kata “dan”, tetapi melengkapinya dengan tanda berupa bulatan. Selain kata-kata
tersebut, penulis surat juga menggunakan tanda berupa tiga titik (…) untuk
memisahkan pokok pikiran satu dengan yang lain, sebagaimana terdapat di baris ke-3,
ke-6, ke-8, dan ke-11. Sementara itu, frasa bahasa Arab “wa ammā ba’du” (baris ke-6)
dijadikan sebagai penanda selesainya “puji-pujian” dan bermulanya isi surat. Di dalam
edisi teks, akan dibubuhkan tanda baca untuk meminimalkan terjadinya ketaksaan.
(3) Penulis surat mencantumkan kata-kata yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh
dialek, yakni kata-kata yang dibentuk oleh kata dasar “paréntah/parintah”, seperti
“memarintah” (baris ke-4), “yang diparintah” (baris ke-8, dua kali), dan
“parintahnya” (baris ke-14). Selain itu, penulis dua kali menuliskan kata “satelah” di
baris ke-11. Di dalam edisi teks, cara penulisan demikian akan tetap dipertahankan.
Hal serupa terjadi dalam penulisan nama dan istilah asing, yakni “Roplis Eskuwir”
(baris ke-3 dan ke-5), “jeneral” (baris ke-5), dan “kupernur” (baris ke-5). Selain
pengaruh dialek, kemungkinan besar, kasus itu juga terjadi karena keterbatasan aksara
untuk mengakomodasi bunyi-bunyi tertentu dalam bahasa asing. Di dalam edisi teks,
kata-kata itu diperbaiki menjadi “Raffles Esquire”, “jenderal”, dan “gubernur”.
(4) Penulis surat menuliskan angka “2” dalam kata ulang “desa-desanya”, sebagaimana
terdapat di baris ke-7. Menurut Sweeney (2008, 204-208), angka “2” merupakan
sebuah tanda dalam aksara Jawi (Arab Melayu) yang tak ternilai harganya. Tanda itu
diciptakan secara khusus untuk menangani satu ciri yang menyeluruh dalam
penggunaan bahasa Melayu, yaitu penggandaan atau reduplikasi. Oleh karena itu, di
dalam edisi teks, cara penulisan demikian akan tetap dipertahankan.
(5) Kata hubung subordinatif atributif ”yang” ditulis dengan dua cara. Ada kalanya ditulis
terpisah dari kata berikutnya, ada kalanya bersambung dengan suku kata (silabe)
pertama pada kata berikutnya. Frasa “yang telah”, misalnya, ditulis dengan dua cara,
yakni disambungkan (baris ke-11) dan dipisahkan (baris ke-14 dan ke-15). Adapun
frasa-frasa yang ditulis secara bersambung adalah “yangdipesertakan” (baris ke-1),
“yangdiparintah” (baris ke-8; dua kali), dan “yangdi dalam” (baris ke-8). Sementara
frasa-frasa yang ditulis secara terpisah adalah “yang terbit” (baris ke-1), “yang suci”
(baris ke-1), “yang amat” (baris ke-1), “yang mauquf” (baris ke-3), “yang ada di
dalam” (baris ke-3), “yang memarintah” (baris ke-4), “yang bernama” (baris ke-5),
“yang beroleh” (baris ke-5), “yang lain” (baris ke-9), “yang pertama” (baris ke-9),
“yang tersebut” (baris ke-13), “yang menjadi” (baris ke-13, ke-14), dan “yang apa”
(baris ke-15). Di dalam edisi teks, kata “yang” langsung dipisahkan dengan kata yang
mengikutinya, tetapi tidak akan dimasukkan ke dalam kategori kesalahan tulis.
(6) Cara menuliskan “Imam Kadi” juga menjadi kekhasan dalam surat ini. Di dalam teks
yang menggunakan aksara Jawi dan bahasa Melayu (baris ke-2), nama itu ditulis
“Imam Qāḍī”. Akan tetapi, di dalam teks yang menggunakan aksara dan bahasa Jawa
(baris ke-19), nama itu ditulis “Imam Kali”. Hal ini mengingatkan penulis pada dua
Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara Vol. 12 No. 2 Tahun 2021 187
Hazmirullah Aminuddin
pucuk surat yang dikirim oleh Sultan Sepuh VII Cirebon untuk Raffles pada tanggal 2
Rabiulakhir 1226 Hijriah (26 April 1811 Masehi) 4 . Satu surat ditulis dengan
menggunakan aksara (dan bahasa) Jawa, sedangkan satu lainnya dalam aksara Jawi
(bahasa Melayu). Di dalam surat beraksara (dan berbahasa Jawa), Sultan Sepuh VII
Cirebon menulis, “...sarta ambakta sěrat amawi cap parénta(h), sarěng kalayan rama
Arya Kidhul, raka Raja Kartaningrat, rayi Arya Sumintaradhya, Radhén
Sudhiradhibrata, Tuměnggung Mangkunagara, Imam Kali” (Hazmirullah 2017, 115).
Sementara itu, dalam surat beraksara Jawi (berbahasa Melayu), ia menulis, “...serta
membawa[‘] surat yang cap dan perintah sama dengan saya punya bapak muda
Pangeran Arya Kidul, dan saya punya kakak Pangeran Raja Karta Ningrat, dan saya
punya adik Pangeran Arya Suminta Raja, dan Raden Sudirabrata, dan Tumeng(g)ung
Mangkune(g)ara, dan Imam Qāḍī” (Hazmirullah 2016, 224). Dalam konteks bahasa
Jawa, frasa “imam kali” ternyata merupakan variasi dari “imam kadi”. Bausastra
Jawa (Tim Balai Bahasa Yogyakarta 2011) memuat kedua lema itu di halaman 313
dan 317. Dalam konteks ini, memang berlaku hukum perubahan bunyi r-d-l,
sebagaimana berlaku terhadap kata “lontar”, “rontal”, dan “dontal” yang bermakna
‘daun tal’. Bahkan, kemungkinan besar, kata “Kali” yang terdapat pada nama Sunan
Kali Jaga juga bermakna ‘kadi’, merujuk kepada posisinya sebagai salah seorang
penghulu di Kesultanan Demak (Hazmirullah 2019, 285).
b) Edisi dan Tranformasi Teks
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami teks surat, penulis menyajikan edisi dan
transformasi teks secara berdampingan. Di dalam edisi teks, penulis juga membubuhkan aparat
kritik jika diperlukan, terutama terhadap suku kata, kata, dan frasa yang dianggap keliru. Aparat
itu berupa ( ) ‘tanda kurung lengkung dengan teks di dalamnya’ disebut addenda dan [ ]
‘tanda kurung siku dengan teks di dalamnya’ disebut disdenda. Tanda addenda berarti ‘huruf,
suku kata, kata, frasa, atau kalimat ditambahkan oleh penulis, tetapi sebaiknya dibaca’.
Sementara tanda disdenda berarti ‘huruf, suku kata, kata, frasa, atau kalimat dan sebaiknya tidak
perlu dibaca’.
Langkah berikutnya adalah perbaikan kasus-kasus salah tulis (emendasi) yang terdapat di
dalam teks naskah objek penelitian. Penulis membubuhkan pungtuasi, tanda yang sebenarnya
tidak terdapat di dalam teks naskah objek penelitian, berdasarkan interpretasi terhadap isi teks
tanpa sebarang indikasi formal dari struktur kalimat. Pada tahap ini, penulis juga memperbaiki
bacaan teks, tetapi akan menghindarkan diri dari tindakan berlebihan dan berpotensi
menimbulkan “bahaya”, yakni membuat perbaikan anakronistik atau hiperkoreksi karena
menggunakan kacamata masa kini (Putten dan Azhar 2006, 37).
Berikut penulis sajikan edisi dan transformasi teks surat tersebut:
Edisi Teks Transformasi
Bahwa inilah surat tulus serta ikhlas yang Inilah surat (yang ditulis dengan) tulus dan
dipesertakan dalamnya beberapa hormat dan ikhlas. Di dalamnya, disertakan pula rasa
khidmat yang terbit daripada hati yang suci putih hormat dan khidmat yang terbit dari hati
lagi jernih yang amat hening, yaitu daripada nan suci putih serta jernih dan bersih. (Surat
sahaya Pangeran Arya Kidul, dan Pangeran Raja ini) ditulis oleh saya, Pangeran Arya Kidul,
Kartaningrat, dan Imam Kadi. Ialah yang mauquf bersama Pangeran Raja Kartaningrat dan
serta senang yang ada di dalam tahta di bawah Imam Kadi, yang tinggal dan merasa senang
4
Kedua surat itu merupakan koleksi British Library dan dimasukkan ke dalam bundel Mss. Eur. D. 742/1.
Surat beraksara (dan berbahasa) Jawa diberi kode Mss. Eur. D. 742/1 f. 49a-b. Sementara surat beraksara
Jawi (berbahasa Melayu) diberi kode Mss. Eur. D. 742/1 f. 49.
188 Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara Vol. 12 No. 2 Tahun 2021
Ketika Pangeran Minta Jabatan: Kajian Filologis terhadap Sepucuk Surat untuk Raffles (1811)
duli Tuan Mister (Raffles Esquire) 5 . berada di dalam takhta, di bawah duli Tuan
Disempurnakan Allah subḥānāhū wa ta’ālā jua Mister Raffles Esquire. (Semoga surat ini)
kiranya kepada Paduka Seri Tuan Besar yang disempurnakan oleh Allah swt (sampai)
memarintah 6 serta atas kuasa segala daerah kepada Paduka Seri Tuan Besar yang
Negeri Betawi dan sekalian Negeri Tanah Jawa, memerintah dan berkuasa atas Negeri
yaitu yang bernama Seri Paduka Tuan Besar Betawi dan seluruh Tanah Jawa, yaitu Seri
(Gubernur) (Jenderal) 7 (Raffles Esquire). Ialah Paduka Tuan Besar Gubernur Jenderal
yang beroleh pangkat martabat kebesaran, dan Raffles Esquire. Dialah yang beroleh
(ketinggian) 8 , dan kemuliaan, serta dilanjutkan pangkat, martabat kebesaran, ketinggian,
Allah usia zaman umurnya, Āmīn yā rabb al- kemuliaan, dan (semoga) dipanjangkan usia
‘ālamīn. oleh Allah swt. Āmīn yā rabb al-‘ālamīn.
Wa ammā ba’du. Kemudian daripada itu, maka Wa ammā ba’du. Selanjutnya, saya
ialah sahaya maklumkan dan menyembahkan beritahukan (sekaligus) persembahkan
daripada Negeri Cirebon dan segala desa2nya. Negeri Cirebon beserta semua desanya
Dan sahaya maklumkan segala negeri yang (kepada Tuan Besar). Saya beritahukan pula
diparintah oleh pétor yang di dalam Negeri semua negeri yang berada di bawah
Cirebon. Adapun negeri yang diparintah oleh perintah pétor yang berada di Negeri
Pétor Cirebon yang lain dari Negeri Cirebon, Cirebon. Negeri-negeri selain Cirebon yang
yaitu yang pertama, Negeri Gebang, dan kedua, dimaksud itu adalah (1) Negeri Gebang, (2)
Negeri Darmayu, dan ketiga, Negeri Sukapura, Negeri Darmayu, (3) Negeri Sukapura, (4)
dan keempat, Negeri Bunagara, dan kelima, Negeri Bunagara (Imbanagara?), (5) Negeri
Negeri Ciamis, dan keenam Negeri Ciancang, dan Ciamis, (6) Negeri Ciancang, dan (7)
ketuju(h)9 Negeri Limbangan. Negeri Limbangan.
Syahdan, satelah sahaya menyembahkan dan Syahdan, setelah saya persembahkan dan
satelah menyelesaikan negeri yang telah tersebut selesaikan (perincian tentang) negeri-negeri
itu, jikalau limpah kurnia dan suka rida, maka tersebut, jikalau ada kelimpahan karunia
ialah supaya Orang Besar percayakan daripada dan kebesaran hati, ada baiknya jika Orang
segala hal ihwalnya Negeri Cirebon dan segala Besar mempercayakan pengelolaan Negeri
negeri yang tersebut itu kepada sahaya orang Cirebon dan semua negeri di sekitarnya
lama. Seperti pasal yang menjadi Raja Kepala kepada saya, orang lama (di Kesultanan
Negeri Cirebon dan yang menjadi Tumenggung Cirebon). (Jabatan yang dipercayakan
Kepala negeri yang telah tersebut itu, atau barang kepada kami), seperti Raja Kepala Negeri
titah parintahnya Orang Besar, atau pasal jual Cirebon, Tumenggung Kepala di salah satu
beli belian akan segala dagangan yang ada di (dari tujuh) negeri yang telah disebutkan,
dalam segala negeri yang telah tersebut itu, maka (pejabat yang menjalankan) perintah Orang
supaya Orang Besar tahu kepada sahaya orang Besar, atau (pejabat yang mengurusi)
lama jua adanya. perdagangan di serata negeri. Semoga
Orang Besar mengenal saya sebagai orang
lama (di Kesultanan Cirebon).
Termaktub di dalam Negeri Betawi, 22 hari dari Ditulis di Batavia, 22 Syaban 1226 H.
bulan Syaban tārīkh al-sanah 1226.
5
(r-w-f-l-s) dan (a-s-k-w-i-r); transposisi.
6
Dipengaruhi oleh dialek; dibentuk dari kata dasar “paréntah/parintah” dalam bahasa lokal; transposisi.
7
Dipengaruhi oleh dialek; transposisi.
8
Kekurangan guratan diagonal di bagian atas fonem /g/; omisi.
9
Kekurangan fonem /h/; omisi.
Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara Vol. 12 No. 2 Tahun 2021 189
Hazmirullah Aminuddin
Punika tandha kaula Pangéran Arya Kidhul Inilah tanda persetujuan saya (atas isi surat
ini), Pangeran Arya Kidul
Punika tandha kaula Pangéran Raja Kartaningrat Inilah tanda persetujuan saya (atas isi surat
ini), Pangeran Raja Kartaningrat.
Punika tandha kaula Imam Kali Inilah tanda persetujuan saya (atas isi surat
ini), Imam Kadi.
c) Kandungan dan Analisis Teks
Sebagaimana diungkapkan di bagian terdahulu, sebenarnya tujuan utama para penulis
surat adalah meminta jabatan kepada Thomas Stamford Raffles, calon penguasa anyar di tanah
Jawa. Peneliti menduga, para penulis surat “menyaksikan” peristiwa penaklukan Batavia pada
bulan Agustus 1811 dan diakhiri dengan penangkapan Gubenur Jenderal Prancis-Belanda Jan
Willem Janssens di wilayah Jawa Tengah. Meskipun demikian, para penulis surat sepertinya
tidak tahu (atau setidaknya belum menerima informasi) bahwa jabatan Raffles berbeda dengan
para pendahulunya dari Negeri Belanda. Buktinya, di dalam surat, Pangeran Arya Kidul dan
kawan-kawan menyebutnya sebagai “Gubernur Jenderal”. Padahal, jabatan Raffles adalah
Letnan Gubernur Jawa dan Wilayah-wilayah taklukannya (Lieutenant-Governor Java and Its
Dependencies). Lagi pun, ia baru secara resmi menduduki jabatan tersebut pada bulan Oktober
1811, sedangkan surat ditulis pada bulan September 1811. Selain itu, di dalam surat tersebut,
Pangeran Arya Kidul dan kawan-kawan mengungkapkan sejumlah informasi penting yang
menarik untuk didedahkan di dalam penelitian ini. Pertama, penggunaan istilah “pétor”. Kedua,
tujuh wilayah administratif yang berada di bawah pengelolaan Pétor Cirebon. Ketiga, para
penulis menyebut mereka sebagai “orang-orang lama” di Kesultanan Cirebon. Keempat, surat
untuk Raffles itu ternyata tidak ditulis di Cirebon, tetapi di Batavia.
(1) Penggunaan Istilah “Pétor”
Di dalam surat, kata “pétor” ditulis sebanyak dua kali, yakni di baris ke-8. Merujuk
Bausastra Jawa (Tim Balai Bahasa Yogyakarta 2011, 539), “pétor” memiliki dua arti, yakni
(1) ‘priyayi pangréh praja bangsa Wlanda (pejabat pemerintah yang berkebangsaan Belanda)’
dan (2) ‘asistén residhén (asisten residen)’. Akan tetapi, di dalam banyak naskah surat, kata
“pétor” secara konsisten diterjemahkan menjadi ‘residen’. Salah satu contohnya dapat dilihat
dalam surat Gubernur Jenderal VOC Willem Arnold Alting10 kepada Sultan Sepuh dan Sultan
Anom Cirebon pada tanggal 4 Juli 179411. Di sana, terdapat kalimat “…yén Pétor ing Gragé,
(Johan Lubbert Umbgrove), sampun akintun ing ngriki dhateng pamersanipun Kangjeng
(Gubernur Jenderal) sarta Para Rat van Indiyah…”. Teks beraksara dan bahasa Jawa itu
diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda12 menjadi “…dat de Resident van Cheribon Johan
Lubbert Umbgrove naar deeze Hoofdplaats ter dispositie van Gouverneur Generaal en de
Raaden van Indien opgezonden heeft…”. Pada ketika surat tersebut ditulis, tokoh yang
menjabat Residen Cirebon adalah Matthijs Waterloo (1769-1812). Ia menduduki jabatan
tersebut sejak tahun 1809 dan tetap menjabat meski kekuasaan atas Jawa telah beralih ke
tangan Inggris. Hal itu seiring dengan surat pengangkatan (kembali) yang diterbitkan Raffles
10
Gubernur Jenderal ke-32 VOC, menjabat pada periode 1780-1797 Masehi.
11
Dua pucuk surat koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang masing-masing diberi kode ID-
ANRI K66a, File 3587, Folio 819-820 dan ID-ANRI K66a, File 3587, Folio 837-838.
12
Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang masing-masing diberi kode ID-ANRI K66a, File
3587, Folio 839-841.
190 Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara Vol. 12 No. 2 Tahun 2021
Ketika Pangeran Minta Jabatan: Kajian Filologis terhadap Sepucuk Surat untuk Raffles (1811)
pada tanggal 17 September 1811. Waterloo meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 1812 dan
jabatan Residen Cirebon diteruskan oleh John Curson Lawrence (Haan 1935, 594, 662).
(2) Wilayah Tugas Pétor Cirebon
Penulis surat mengungkapkan bahwa selain Cirebon, terdapat tujuh daerah yang berada
di bawah pengelolaan Pétor Cirebon. Ketujuh daerah itu adalah (1) Gebang, (2) Darmayu, (3)
Sukapura, (4) Bunagara, (5) Ciamis, (6) Ciancang, dan (7) Limbangan. Kita ketahui bahwa
kini Gebang merupakan nama salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, Darmayu
merupakan nama lain dari Indramayu, Sukapura merupakan nama lawas wilayah Tasikmalaya
sekarang, Ciamis merupakan nama sebuah kabupaten di Jawa Barat, dan Limbangan
merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Garut. Akan tetapi, pada masa lampau, seperti
apa kedudukan daerah-daerah itu? Pertanyaan berikutnya, di manakah lokasi Bunagara dan
Ciancang, sebagaimana dimaksud di dalam surat tersebut? Tetapi, sebelum membahas ketujuh
daerah tersebut pada ketika surat ditulis, penulis akan terlebih dahulu membawa pembaca
untuk menelusuri sejarah hingga ke awal abad ke-18 M.
Meskipun VOC merebut Jakarta pada tahun 1619, pengakuan secara resmi tentang
batas-batas wilayah kekuasaan maskapai dagang Belanda itu baru diperoleh pada tahun 1677.
Penguasa Mataram, Sultan Amangkurat II (1677-1703) menandatangani traktat yang telah
dirintis oleh sang ayah, Sultan Tegalwangi (Amangkurat I; menjabat pada periode 1646-1677),
pada tahun 1652 (Jonge 1873, 166). Momentum penyerahan wilayah pada 1677 itu juga
dicatat dalam sebuah babad dari Cirebon (Holle 1869, 331). Kalakian, Amangkurat II
menegaskan batas-batas tersebut secara tertulis disertai tambahan wilayah kepada
VOC sebagai “pernyataan rasa bersalah” (schuldige danckbaerheit). Wilayah itu berada di
antara Sungai Citarum dan Cipamanukan. Dengan demikian, melalui traktat tertanggal 19-20
Oktober 1677 itu, wilayah kekuasaan VOC bertambah luas, meliputi Kampungbaru (Bogor;
Buitenzorg), Cianjur, Jampang, Cibalagung, Cikalong, Karawang, Wanayasa, Adiarsa, Ciasem,
Pamanukan, Pagaden, Bandung, Timbanganten, Batulayang, dan Parakanmuncang.
Kemungkinan besar, pada saat itu, wilayah kekuasaan VOC juga mencakup Sumedang,
Limbangan, dan Sukapura (Rees 1880, 53-54). Informasi ini pun diperkuat oleh sebuah
dokumen berupa daftar –yang disebut-sebut paling awal—tentang jumlah penduduk, lahan
garapan dan hasil pertanian, serta pajak yang wajib dibayar di kawasan Priangan. Daftar itu
dibuat pada tahun 1686 oleh dua pegawai VOC bernama Claes Hendriksz dan Jan Carstensz.
Dari daftar itu, diperoleh pula informasi mengenai tujuh distrik utama di dataran tinggi
Priangan, yakni Gabangh (terdiri atas 42 dusun/desa; 581 rumah tangga), Cawassin (43
dusun/desa; 398 rumah tangga), Soukapoera (108 dusun/desa; 1.144 rumah tangga),
Bandongh (77 dusun/desa; 1.056 rumah tangga), Parcamountsiang (35 dusun/desa; 872 rumah
tangga), Sammadangh (181 dusun/desa; 953 rumah tangga), dan Indramayou (22 dusun/desa;
284 rumah tangga) (Fernando 2013; Haan 1912, 202-203).
Pada awal abad ke-18 Masehi, VOC telah menguasai wilayah yang begitu luas,
terutama di bagian barat pulau Jawa. Hal itu seiring dengan keberhasilan Kompeni menguasai
hampir semua aspek kehidupan penduduk pribumi, utamanya di bidang politik, ekonomi, dan
hukum (Hoadley 2009, 458). Penguasaan di segala aspek kehidupan itu berjalan maksimal
karena didukung oleh setidaknya tiga faktor. Pertama, bertambahnya pengetahuan VOC
terhadap wilayah pedalaman Jawa. Kedua, meningkatnya kecenderungan penduduk untuk
hidup menetap (sedentary), terutama di pedalaman Priangan. Ketiga, ditemukannya kopi,
komoditas baru dan sangat menguntungkan, pada awal abad ke-18 Masehi (Hazmirullah 2019,
278-279). Sebenarnya, semua hasil yang didapat oleh Kompeni bermula dari keterpaksaan.
Pada paruh kedua abad ke-17 M, VOC memasuki wilayah pedalaman Jawa karena keharusan
berpihak di medan konflik kekuatan politik pribumi, terutama di Kesultanan Mataram
(Breman 2014, 15). Pada awal abad ke-18 M itu, terdapat setidaknya 17 kabupaten di bagian
Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara Vol. 12 No. 2 Tahun 2021 191
Hazmirullah Aminuddin
barat pulau Jawa, kecuali Batavia yang merupakan pusat kekuasaan VOC. Ketujuh belas
kabupaten itu adalah Limbangan, Sumedang, Parakanmuncang, Bandung, Sukapura, Galuh,
Timbanganten, Gebang, Indramayu, Pamanukan dan Pagaden, Ciasem, Karawang, Cianjur,
Bojonglopang, Bojongmalang, Utama, dan Pamotan (Rees 1880, 65-67). Arkian, wilayah
yang demikian luas itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni wilayah Jakarta (Het
Jacatrasche gebied) dan Priangan yang sesungguhnya (Het Eigenlijke Priangan). Wilayah
Jakarta dibagi lagi menjadi empat bagian, yakni Stad (Kota) Batavia, de Ommelanden (Daerah
Sekitar), de Benedenlanden (Daerah Dataran Rendah), dan de Bovenlanden (Daerah Dataran
Tinggi) (Klein 1931, 130-131).
Pada periode 1705-1730 M, ketika berada di bawah kendali Pangeran Aria Cirebon,
wilayah Priangan terdiri atas sembilan kabupaten, yakni Limbangan, Sukapura, Galuh,
Sumedang, Bandung, Parakanmuncang, Ciasem, Pamanukan, dan Pagaden. Akan tetapi, pada
tahun 1730, hanya terdapat tiga kabupaten yang di bawah perintah Residen Cirebon, yakni
Limbangan, Sukapura, dan Galuh. Sementara itu, Kabupaten Sumedang, Bandung, dan
Parakanmuncang, per tanggal 12 Mei 1730, dimasukkan sebagai bagian dari wilayah Batavia.
Pada periode 12 Mei 1765-28 Mei 1758, ketiga daerah itu kembali dimasukkan ke dalam
wilayah administratif Cirebon. Setelah itu, Sumedang, Bandung, dan Parakanmuncang
dikembalikan ke Batavia dan membentuk satu kabupaten bernama Bataviasche-Preanger atau
Jacatrasche-Preanger. Sementara soal nasib tiga kabupaten lain, yakni Ciasem, Pamanukan,
dan Pagaden, tidak ditemukan informasi akurat (Klein 1931, 132).
Dengan demikian, secara umum, kabupaten-kabupaten di wilayah Priangan dapat dibagi
menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah Limbangan, Sukapura, Galuh. Pada tahun
1705, ketiganya merupakan bagian dari Cirebon untuk membentuk wilayah bernama
Kabupaten Cirebon-Priangan (Cheribonsche-Preanger Regentschappen). Kelompok kedua
dihuni oleh Sumedang, Bandung, dan Parakanmuncang. Pada periode 1730-1758, ketiganya
menjadi bagian dari Kabupaten Batavia-Priangan (Bataviasche-Preanger Regentschappen)13.
Setelah sempat menjadi bagian dari Cirebon, pada periode 1758-1765, ketiga daerah tersebut
dikembalikan ke Batavia. Sementara itu, kelompok ketiga dihuni oleh Cianjur, Kampungbaru
(Buitenzorg), Tangerang, Karawang, Ciasem, dan Pagaden. Semua wilayah itu menjadi bagian
dari daerah Dataran Tinggi dan Dataran Rendah Jakarta (Jacatrasche Boven- en
Benedenlanden) (Klein 1931, 132-133). Kabupaten Pagaden dihapuskan pada 1798 (Chijs
1894, 901). Sementara itu, pada tahun 1802, Kabupaten Galuh, Imbanagara, dan Utama
digabungkan menjadi Kabupaten Galuh. Hal itu lantaran Bupati Imbanagara dan Utama
dianggap tidak bisa mengatur pemerintahan sendiri sehingga menimbun utang sebesar 23.500
rijkdaalders. Untuk selanjutnya, pembayaran utang tersebut dibebankan kepada Bupati Galuh
(Lubis 1998, 86-87).
Ketika Daendels memulai jabatan pada tahun 14 Januari 1808, pulau Jawa terbagi
menjadi tiga bagian. Pertama, Kota Batavia, daerah sekitar (de ommelanden), serta
Jakkatrasche en Preanger-Regentschappen yang meliputi Tangerang, Karawang, Buitenzorg,
Cianjur, Sumedang, Bandung, dan Parakanmuncang. Wilayah ini dihuni oleh penduduk yang
berjumlah tak kurang dari 200.000 jiwa. Kedua, Kesultanan Cirebon beserta tiga daerah yang
disebut Cheribonsche Preanger-Regentschappen (meliputi Limbangan, Sukapura, dan Galuh).
Diperkirakan, wilayah tersebut dihuni oleh penduduk sebanyak 350.000 jiwa. Ketiga, wilayah
Pantai Timur Laut (Noord-Oostkust) dan Ujung Timur (Oosthoek) yang berpenduduk tak
kurang dari 1,6 juta jiwa (Rees 1880, 110). Setahun berselang, tepatnya pada tanggal 2
Februari 1809, Daendels menerbitkan Peraturan tentang Pengelolaan Wilayah Cirebon
13
Istilah “regentschap” di sini sebenarnya tidak tepat diterjemahkan menjadi ‘kabupaten’, tetapi setara dengan
landdrost-ambt yang kelak diperkenalkan oleh Daendels pada tahun 1809 atau keresidenan yang
diperkenalkan oleh Raffles pada tahun 1813.
192 Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara Vol. 12 No. 2 Tahun 2021
Ketika Pangeran Minta Jabatan: Kajian Filologis terhadap Sepucuk Surat untuk Raffles (1811)
(Reglement op het Beheer van de Cheribonsche-landen) 14 . Di dalam Ketentuan Umum
(Algemeene Bepalingen) disebutkan bahwa wilayah Cirebon dibagi menjadi dua prefektur.
Pertama, Sulthans-landen, mencakup wilayah utara yang kini diduduki oleh Kesultanan
Cirebon, termasuk wilayah “Kepangeranan” (het Prinsdom) Gebang. Kedua, Cheribonsche
Preangerlanden yang mencakup wilayah Kabupaten Limbangan, Sukapura, dan Tanah Galuh.
Daendels menyerahkan pengelolaan tiap-tiap prefektur tersebut kepada seorang prefek (Chijs
1896, 474-475; Rees 1880, 110). Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang termaktub di dalam
Pasal 1 Bagian Kedua, ketiga sultan di Cirebon dianggap dan diperlakukan sebagai pegawai
Yang Mulia Raja Belanda. Secara struktural, mereka berada langsung di bawah prefek
(pejabat kolonial setingkat residen) 15 dan dianugerahi jabatan hoofd-regent atau masyhur
disebut wedana (Atja 1988, 39). Meskipun demikian, ketiga sultan di Cirebon tersebut tetap
diperkenankan untuk menggunakan tanda-tanda kebesaran dan tata cara penghormatan yang
sebelumnya berlaku di lingkungan kesultanan. Kebijakan itu dimaksudkan untuk menjaga
citra para sultan di mata rakyat (Chijs 1896, 482-483). Daendels kemudian mengubah istilah
prefektur menjadi landdrostambten, wilayah administratif yang juga setingkat keresidenan.
Seiring dengan perubahan istilah wilayah, sebutan prefek pun diubah menjadi landdrost
(Hardjasaputra 2002, 40). Satu hal yang menarik, di dalam regulasi itu, Daendels tak
menyebut Galuh sebagai regentschappen (kabupaten) sebagaimana Limbangan dan Sukapura,
tetapi het land Galoe (Tanah Galuh). Penulis berpendapat, penggunaan istilah itu
mengindikasikan bahwa di wilayah bekas Kerajaan Galuh, terdapat sejumlah wilayah
administratif yang memiliki pemerintahan sendiri. Dalam konteks surat Pangeran Arya Kidul
dan kawan-kawan, daerah-daerah itu adalah Bunagara (kemungkinan besar, yang dimaksud
adalah Imbanagara), Ciamis, dan Ciancang.
Sebagai tindak lanjut dari peraturan tanggal 2 Februari 1809, Daendels menerbitkan
peraturan khusus untuk pembentukan Cheribonsche Preangerlanden pada tanggal 31 Maret
1809. Akan tetapi, aturan itu hanya bertahan selama setahun. Soalnya, pada tanggal 20 Juni
1810, ia menerbitkan aturan anyar, di mana Limbangan, Sukapura, dan Galuh digabungkan
dengan Regentschappen Jakkatrasche en Preanger-Bovenlanden. Melalui regulasi itu pula,
Daendels memutuskan untuk menggabungkan wilayah Jakkatrasche en Preanger-
Bovenlanden serta Cheribonsche Preanger-Regentschappen ke dalam satu wilayah
administratif yang dinamai Landdrost-ambt Jaccatrasche en Cheribonsche Preanger-
Regentschappen. Aturan kembali diubah seiring dengan pemisahan Karawang menjadi
landdrost-ambt baru. Selanjutnya, nama untuk Landdrost-ambt Jaccatrasche en Cheribonsche
Preanger-Regentschappen menjadi lebih sederhana, yakni Landdrost-ambt Bataviasche-
Regentschappen. Arkian, perbatasan semua wilayah administratif itu dijabarkan melalui
sebuah ketetapan yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 1811 (Rees 1880, 110-111). Melalui
regulasi ini pula, Daendels memutuskan untuk menghapuskan Kabupaten Limbangan dan
Sukapura. Wilayah bekas dua kabupaten itu kemudian diagih-agih ke sejumlah kabupaten
yang berada di Landdrost-ambt Jaccatrasche and Cheribonsche Preanger Regentschappen,
Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakanmuncang (Chijs 1897, 591; Rees 1880, 113).
Sementara itu, seluruh wilayah Galuh—yang disebut sebagai daerah terpencil dan minus
(bahkan tidak ada sama sekali) potensi kopi—digabungkan dengan Kesultanan Yogyakarta.
Hal itu tercantum di dalam kontrak antara Pemerintah Belanda dan Pangeran Adipati Anom
14
Peraturan tersebut terdiri atas: Ketentuan Umum (6 pasal); Bagian Pertama, Perihal Prefek (32 pasal); Bagian
Kedua, Perihal Para Sultan, Bupati, dan Pemerintahan Daerah Lebih Lanjut (31 pasal); Bagian Ketiga,
Perihal Pajak, Kerja Pengabdian, dan Kewajiban-kewajiban Lain Penduduk Pribumi (16 pasal); Bagian
Keempat, Perihal Pengadilan Negeri (11 pasal); Bagian Kelima, Perihal polisi, Pembuatan Jalan, dan
Layanan Pos (31 pasal) (Chijs 1896, 474-513).
15
“De drie Sulthans der Cheribonsche landen zullen voortaan worden beschouwd en behandeld als
ambtenaren van Zijne Majesteit den Koning van Holland en in rang onmiddelijk volgen op den prefect...”
Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara Vol. 12 No. 2 Tahun 2021 193
Hazmirullah Aminuddin
Mangkunegara, salah seorang bupati Kesultanan Yogyakarta sekaligus penanggung jawab
dataran tinggi Jawa, pada tanggal 10 Januari 1811 (Rees 1880, 113-114).
Dengan demikian, hingga masa pemerintahan Daendels berakhir pada tahun 1811,
ketujuh daerah yang disebut di dalam surat Pangeran Arya Kidul dan kawan-kawan tidak lagi
berstatus kabupaten. Secara administratif, daerah Gebang, Indramayu, sebagian Limbangan,
dan sebagian Sukapura berada bergabung dengan Landdrost-ambt Jaccatrasche and
Cheribonsche Preanger Regentschappen. Sementara itu, tiga daerah di Tanah Galuh, yakni
Imbanagara, Ciamis, dan Ciancang, berada di wilayah administratif Kesultanan Yogyakarta.
Meskipun demikian, wilayah itu tetap memiliki pemerintahan sendiri. Menurut Lubis (2000a,
23), pada tahun 1811, ketiga daerah itu masing-masing dikelola oleh seorang patih. Akan
tetapi, merujuk surat Pangeran Arya Kidul dan kawan-kawan, ketiga daerah itu dipimpin oleh
seorang “tumenggung kepala”. Selain itu, kita memperoleh informasi pula bahwa ternyata
ketujuh daerah tersebut masih tetap berada dalam kekuasaan Pétor Cirebon. Sejauh ini,
penulis tidak/belum menemukan bukti bahwa Raffles mengabulkan permohonan ketiga
penulis surat.
(3) Siapakah Para Penulis Surat?
Berdasarkan penelusuran penulis, nama Pangeran Arya Kidul di Kesultanan Cirebon
muncul pada masa-masa awal pemerintahan Sultan Sepuh VII Cirebon (1791-1816). Sosoknya
disinggung di dalam surat Gubernur Jenderal VOC Willem Arnold Alting tertanggal 22
Januari 179316 sehingga cukup beralasan jika Pangeran Arya Kidul menyebut dirinya sebagai
“orang lama” di Kesultanan Cirebon. Di dalam surat itu, Alting mengaku telah menerima surat
berisi permohonan maaf dari Sultan Sepuh VII Cirebon atas kesalahan yang telah diperbuat
oleh Pangeran Arya Kidul. Alting juga berharap agar Sultan Sepuh VII Cirebon
mengusahakan agar Pangeran Arya Kidul—yang telah melarikan diri—segera kembali ke
keraton untuk selanjutnya menghadap Pétor Cirebon Johan Lubbert Umbgrove. Alting juga
memberikan jaminan bahwa Pangeran Arya Kidul akan diperlakukan secara hormat asal mau
mengakui kesalahan di hadapan semua kerabat keraton dan Pétor Cirebon (Hazmirullah 2018,
291-292). Isi surat Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting mengindikasikan bahwa
Pangeran Arya Kidul telah melakukan tindakan yang tidak disukai oleh Kompeni. Hanya,
setakat ini, penulis tidak/belum memperoleh informasi akurat mengenai sepak terjang
Pangeran Arya Kidul sehingga membuatnya melarikan diri.
Satu hal yang pasti, Pangeran Arya Kidul berhasil ditangkap (atau mungkin juga
menyerahkan diri). Alih-alih diperlakukan secara terhormat, sebagaimana janji Willem Arnold
Alting, ia malah menerima hukuman berupa pembuangan ke Malaka. Penulis memang
tidak/belum memperoleh informasi akurat, sejak kapan Pangeran Arya Kidul menjalani
hukuman di Malaka. Meskipun demikian, penulis memperoleh informasi bahwa Pangeran
Arya Kidul meninggalkan Malaka pada 23 Desember 1810 (26 Zulkaidah 1225 H). Ia
menumpang kapal bersama tiga utusan Raffles, yakni Tengku Pangeran Siak17, John Scott18,
16
Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia dengan kode ID-ANRI K66a, File 3587, Folio 737-740.
17
Tokoh ini juga dikenal sebagai Tengku Pangeran Sukma Dilaga (kerap juga ditulis Kusuma Dilaga) dan
Sayid Zain. Bahkan, ia juga dijuluki sebagai Pangeran Perca dan memiliki nama yang lebih panjang, yakni
Sayid Zain Balfagih (Adam 2009, 137). Akan tetapi, sumber lain mencatat bahwa nama panjang tokoh
tersebut adalah Sayid Zain Aljufri. Tengku Pangeran Siak merupakan sosok penting untuk memuluskan
rencana Inggris menduduki pulau Jawa. Ia menjadi salah seorang agen kepercayaan Raffles dan memainkan
peran yang sangat krusial, terutama dalam hal berkomunikasi dan “merayu” para penguasa di serata wilayah
Melayu. Apalagi, ia dinilai sebagai sosok yang loyal, tulus, dan berintegritas (Adam 2009, 137-138). Tak
heran jika kemudian Raffles, di dalam sebuah surat kepada Lord Minto, menyebut Tengku Pangeran Siak
sebagai best assistant (Wurtzburg 1986, 118, sebagaimana disitat oleh Gallop 1994, 149).
18
Ia bergabung dengan Raffles atas rekomendasi John Leyden. Akan tetapi, sebenarnya, Raffles tidak
menyukai sikap Scott. Ia juga mengaku tak percaya bahwa Scott merupakan pelaut berpengalaman (Adam
194 Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara Vol. 12 No. 2 Tahun 2021
Ketika Pangeran Minta Jabatan: Kajian Filologis terhadap Sepucuk Surat untuk Raffles (1811)
dan Haji Muhammad Ali 19 , yang ditugaskan untuk mengirim surat dukungan dari para
penguasa Tanah Melayu, termasuk Jawa, terhadap rencana penaklukan Jawa. Ternyata,
petinggi Kesultanan Cirebon yang menumpang kapal itu tak hanya Pangeran Arya Kidul,
tetapi terdapat lima orang lainnya. Informasi ini termaktub di dalam surat Tengku Pangeran
Siak untuk Raffles tertanggal 15 April 1811 (25 Rabiulawal 1226 H) (Hazmirullah, Ma’mun,
dan Darsa 2016, 82)20. Di dalam surat itu, Tengku Pangeran Siak menulis “…Maka kita pun
pikirlah, karena perahu pun tiada tahan bergelombang, maka masuklah kita ke dalam Jambi
karena kita mau mencari perahu yang besar sedikit karena itu perahu kecil-kecil, terlalu
banyak susah. Dan lagi, membawa itu pangeran-pangeran Cirebon itu, enam orang…”.
Identitas keenam petinggi Kesultanan Cirebon yang menumpang kapal dari Malaka itu baru
terungkap di dalam surat balasan Sultan Sepuh VII Cirebon untuk Raffles tertanggal 26 April
1811 (2 Rabiulakhir 1226 H)21. Pada hari itu, Sultan Sepuh VII mengaku bertemu langsung
dengan Tengku Pangeran Siak (yang diantar oleh Ngabei Wiralodra, penguasa Indramayu)22.
Sultan Sepuh mengungkapkan, selain membawa surat (dan juga hadiah dari Raffles), Tengku
Pangeran Siak juga mengajak enam petinggi kesultanan Cirebon, yakni Pangeran Arya Kidul,
Pangeran Raja Kartaningrat, Pangeran Arya Suminta Raja, Raden Sudirabrata, Tumenggung
Mangkunegara, dan Imam Kadi (Hazmirullah 2016, 216, 224).
Di dalam surat itu, Sultan Sepuh VII Cirebon juga mengungkapkan hubungan
kekerabatannya dengan keenam petinggi kesultanan tersebut. Pangeran Arya Kidul disebutnya
sebagai “bapak muda” (versi Melayu) dan “rama” (versi Jawa) (Hazmirullah 2016, 224; 2017,
115). Kedua kata itu dapat diartikan sebagai ‘paman’. Hal ini bersesuaian dengan isi surat
Willem Arnold Alting tanggal 22 Januari 1793 yang menyebut Sultan Sepuh VII Cirebon
sebagai keponakan Pangeran Arya Kidul (Hazmirullah 2018, 291). Dengan demikian, terdapat
kemungkinan bahwa Pangeran Arya Kidul merupakan salah seorang adik dari Sultan Sepuh
VI Cirebon, Sultan Tajul Ngaripin Muhammad Hasanudin. Di dalam surat tersebut, Sultan
Sepuh VII Cirebon menyebut Pangeran Raja Kartaningrat sebagai “kakak” (raka) dan
Pangeran Arya Sumintaraja sebagai “adik” (rayi). Namun, penulis tidak/belum memperoleh
informasi akurat mengenai kedua tokoh tersebut. Hal itu mengingat kata “kakak” dan “adik”
tidak hanya merujuk kepada kakak dan adik kandung, tetapi juga bisa juga merujuk pada
sepupu ataupun anggota keluarga dekat lainnya. Satu hal yang perlu dipertimbangkan, Sultan
Sepuh VII Cirebon merupakan putra sulung Sultan Sepuh VI dan naik takhta pada saat
berumur 10 tahun. Tentu saja, ia tak memiliki kakak. Dengan demikian, Pangeran Raja
Kartaningrat yang menulis surat bersama Pangeran Arya Kidul bukanlah kakak kandung
Sultan Sepuh VII Cirebon, tetapi masih bagian dari kerabat dekat Kesultanan Cirebon.
Sementara itu, Sultan Sepuh VII Cirebon tidak mengungkapkan hubungan kekeluargaannya
dengan Raden Sudirabrata, Tumenggung Mangkunegara, dan Imam Kadi. Meskipun
demikian, penulis dapat memastikan bahwa mereka merupakan bagian dari anggota keluarga
(sentana) Kesultanan Cirebon.
2009, 33). John Scott berpisah dengan Tengku Pangeran Siak di Lingga. Scott kembali ke Malaka, sedangkan
Tengku Pangeran Siak meneruskan pelayaran ke Jawa dengan terlebih dahulu singgah ke beberapa tempat,
seperti Pulau Berhala, Jambi, dan Muntok (Bangka). Ia tiba di Indramayu pada tanggal 26 April 1811 petang
(untuk selanjutnya menuju Cirebon, diantar oleh Ngabei Wiralodra).
19
Utusan Raffles yang ditugaskan untuk mengantarkan surat ke Mataram. Ia berpisah dengan Tengku Pangeran
Siak di di Singkep (Hazmirullah, Ma’mun, dan Darsa 2016, 82).
20
Koleksi British Library dengan kode MSS Eur. D. 742/1, f. 121. Surat ini ditulis di Muntok, Bangka dan
merupakan salah satu rangkaian dari lima surat yang ditulis Tengku Pangeran Siak dalam pelayarannya ke
Jawa (Desember 1810-April 1811)
21
Koleksi British Library dengan kode MSS Eur. D. 742/1, f. 49. Surat ini ditulis dalam dua versi, yakni (1)
aksara Jawi (bahasa Melayu) dan (2) aksara (dan bahasa) Jawa.
22
Informasi ini termaktub di dalam surat Ngabei Wiralodra untuk Raffles pada tanggal yang sama (koleksi
British Library dengan kode MSS Eur. D. 742/1, f. 48.
Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara Vol. 12 No. 2 Tahun 2021 195
Hazmirullah Aminuddin
(4) Mengapa Surat Ditulis di Batavia?
Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, Pangeran Arya Kidul dan kawan-
kawan menulis surat di Batavia, bukan di Cirebon. Mengapa demikian? Penulis
menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut di dalam surat balasan Sultan Sepuh VII
Cirebon untuk Raffles tertanggal 26 April 1811. Sultan Sepuh VII Cirebon menyatakan
bahwa ia enggan menerima keenam petinggi Kesultanan Cirebon tersebut lantaran takut
ketahuan oleh anggota pasukan Belanda (Hazmirullah 2016, 216, 224)23. Kemungkinan,
keenam petinggi Kesultanan Cirebon itu tidak kembali ke Malaka bersama Tengku
Pangeran Siak, tetapi diturunkan di Batavia. Pasalnya, setakat ini, penulis tidak/belum
menemukan informasi akurat mengenai hal itu. Lagi pun, nama mereka tidak tercatat
berada dalam armada ekspedisi Inggris—sebanyak 100 kapal—yang memulai perjalanan
dari Malaka pada 11 Juni 1811 dan tiba di perairan Cilincing pada 30 Juli 1811. Keenam
petinggi Kesultanan Cirebon itu “menyaksikan” kejatuhan Batavia dan benteng kuat
Meester Cornelis (Jatinegara sekarang) pada tanggal 10 Agustus 1811 dan 26 Agustus
1811. Kemungkinan pula, mereka juga mengetahui informasi mengenai pelarian Gubernur
Jenderal Prancis-Belanda Jan Willem Janssens dari Batavia ke Bogor, lalu berpindah ke
Semarang dan Salatiga. Keenam petinggi Kesultanan Cirebon menyadari, tak lama lagi,
kekuasaan atas tanah Jawa bakal berpindah ke tangan Inggris. Kesempatan itulah yang
mereka manfaatkan untuk menulis surat kepada Raffles sekaligus menginformasikan
bahwa mereka layak dipercaya menjadi pengelola wilayah. Pada akhirnya, Jan Willem
Janssens memang tertangkap, lalu menyerahkan kekuasaan atas tanah Jawa kepada Inggris
melalui Kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Secara kebetulan, Pangeran Arya
Kidul dan kawan-kawan menulis surat pada hari yang sama dengan penerbitan
“Proklamasi Pembentukan Pemerintahan Jawa” oleh Gubernur Jenderal East India
Company Lord Minto menerbitkan “Proklamasi Pembentukan Pemerintahan Jawa”.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan paparan di bagian sebelumnya, penulis dapat menyatakan beberapa hal berikut:
Pertama, Pangeran Arya Kidul, Pangeran Raja Kartaningrat, dan Imam Kadi memiliki alasan yang
cukup kuat untuk menyebut diri mereka sebagai “orang lama” di Kesultanan Cirebon. Soalnya,
eksistensi mereka di kesultanan dapat ditelusuri setidaknya hingga ke awal masa pemerintahan
Sultan Sepuh VII Cirebon, tepatnya tahun 1793. Kedua, Pangeran Arya Kidul dan kawan-kawan
memberikan informasi penting, terutama terkait dengan wilayah tugas Pétor Cirebon Matthijs
Waterloo. Selain pusat Kesultanan Cirebon (Sulthans-landen), Waterloo juga ditugaskan untuk
mengelola tujuh daerah lain, yakni Gebang, Indramayu, Sukapura, Bunagara (Imbanagara),
Ciamis, Ciancang, dan Limbangan, meski berada di wilayah administratif yang berbeda-beda.
Dengan demikian, wilayah tugas Pétor Cirebon tidak mengikuti wilayah administratif yang
dibentuk pada masa pemerintahan Daendels. Ketiga, Pangeran Arya Kidul dan kawan-kawan
menulis surat di Batavia, bukan di Cirebon. Hal itu terjadi karena Sultan Sepuh VII Cirebon
enggan menerima kehadiran mereka karena takut ketahuan oleh pasukan Prancis-Belanda yang
kala itu masih berkuasa. Oleh karena itu, Tengku Pangeran Siak-yang membawa mereka dari
Malaka-memutuskan untuk menyinggahkan mereka di Batavia.
Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Pasalnya,
masih terdapat sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Sejauh ini, penulis tidak/belum berhasil
menemukan informasi akurat mengenai jati diri para penulis surat, terutama Pangeran Arya Kidul.
23
“Dan lagi, daripada hal orang enam itu, saya balikkan lagi bersama Ten(g)ku Pangeran karena tiada kuasa
menyimpan dia, takut kepada Holanda”.
196 Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara Vol. 12 No. 2 Tahun 2021
Ketika Pangeran Minta Jabatan: Kajian Filologis terhadap Sepucuk Surat untuk Raffles (1811)
Akan tetapi, fakta sejarah menyatakan bahwa VOC merasa terganggu oleh sepak terjang Pangeran
Arya Kidul pada awal dekade tahun 1790. Apa sesungguhnya yang terjadi di Kesultanan Cirebon
kala itu? Fakta sejarah juga menyatakan bahwa Pangeran Arya Kidul menerima hukuman
pembuangan ke Malaka. Ternyata, ia tak sendiri, tetapi bersama lima petinggi Kesultanan Cirebon
lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan serangkaian penelitian lanjutan untuk menjawab berbagai
pertanyaan tersebut sekaligus mengungkap fakta sejarah yang berlaku di Kesultanan Cirebon,
setidaknya pada dekade akhir abad ke-18 Masehi hingga dekade awal abad ke-19 Masehi.
DAFTAR PUSTAKA
Adam, Ahmat. Letters of Sincerity: The Raffles Collection of Malay Letters (1780-1824) A Descriptive
Account with Notes and Translation. Kuala Lumpur: The Malaysian Branch of the Royal
Asiatic Society. 2009.
Atja. "Menjelang Penetapan Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Cirebon". Laporan Penelitian.
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. 1988.
Baried, Siti Baroroh, et al. Pengantar Teori Filologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1985.
Breman, Jan. Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa, Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di
Jawa, 1720-1870. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.
Chijs, J. A. van der. Plakaatboek, 1602-1811. Twaalfde Deel (1795-1799). Batavia/’S Hage:
Landsdrukkerij/M. Nijhoff. 1894.
_______________. Plakaatboek, 1602-1811. Vijftiende Deel (1808-1809). Batavia/’s Hage:
Landsdrukkerij/M. Nijhoff. 1896.
_______________. Plakaatboek, 1602-1811. Zestiende Deel (1810-1811). Batavia/’s Hage:
Landsdrukkerij/M. Nijhoff. 1897.
Fathurahman, Oman. 2015. Filologi Indonesia: Teori dan Metode. Jakarta: Prenadamedia Group. 1897.
Fernando, M. Radin. "Sebuah daftar masa lalu terkait desa, kepala desa, rumah tangga, upeti dan
penghasilan di Priangan, Jawa Barat, 1686". Dalam Harta Karun. Khazanah Sejarah Indonesia
dan Asia-Eropa dari Arsip VOC di Jakarta, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia. 2013.
Gallop, Annabel Teh. The Legacy of The Malay Letter (Warisan Warkah Melayu). London: British
Library. 1994.
Haan, Frederik de. Priangan: De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811.
Derde Deel. Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 1912.
______________. “Personalia der Periode van het Engelsch Bestuur over Java 1811-1816.” Bijdragen
tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 92., No. 1 (1935): 477–681.
Hardjasaputra, Sobana. “Perubahan Sosial di Bandung 1810-1906.” Disertasi Doktoral. Depok:
Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. 2002.
Hazmirullah. "Surat Balasan Sultan Sepuh VII Cirebon untuk Raffles: Kajian Strukturalisme Genetik".
Metasastra, Vol. 9., No. 2 (2016): 211–224.
__________. "Surat-surat Thomas Stamford Raffles dan Sultan Sepuh VII Cirebon: Edisi Teks,
Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara Vol. 12 No. 2 Tahun 2021 197
Hazmirullah Aminuddin
Makna Posisi Cap, dan Gambaran Kondisi Sosial Politik Tahun 1810-1812". Bandung:
Universitas Padjadjaran. 2017
__________. "Pemberontakan Pangeran Arya Kidul dan Serangan Prancis Terhadap Belanda Dalam
Surat Gubernur Jenderal VOC Tahun 1793". Dalam Mengungkap Selaksa Makna yang
Terpendam Dalam Budaya Nusantara, 285–297. Bandung: Raness Media Rancage. 2018.
__________. "Sistem Peradilan di Pulau Jawa pada Masa Pemerintahan Inggris (1811-1816) Dalam
Naskah Kitab Hukum Raffles". Bandung: Universitas Padjadjaran. 2019.
Hazmirullah, Titin Nurhayati Ma’mun, dan Undang Ahmad Darsa. "Surat-surat Tengku Pangeran
Siak: Sebuah Reportase Perjalanan untuk Raffles". Manuskripta, Vol. 6., No. 1 (2016): 67–91.
Hoadley, Mason C. Islam dalam Tradisi Hukum Jawa & Hukum Kolonial. Yogyakarta: Graha Ilmu.
2009.
Holle, K.F. "Geschiedenis der Preanger-Regentschappen". Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en
Volkenkunde, Deel XVII, 316–367. Batavia/’s Hage: Lange & Co/M. Nijhoff,. 1869.
Jonge, JKJ de. De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie, VII. ’S
Gravenhage/Amsterdam: Martinus Nijhoff/Frederik Muller. 1873.
Klein, Jacob Wouter de. Het Preangerstelsel (1677-1871) en Zijn Nawerking. Delft: N.V. Technische
Boekhandel en Drukkerij J. Waltman Jr. 1931.
Lubis, Nina H. Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan
Sunda. 1998.
____________. "Galuh (Ciamis)". Dalam Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat, 9–26. Bandung:
Alqaprint,. 2000.
Putten, Jan van der, dan Al Azhar. Dalam Berkekalan Persahabatan: Surat-surat Raja Ali Haji kepada
Von de Wall. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2006.
Rees, Otto van. "Overzigt van de Geschiedenis der Preanger-Regentschappen". Verhandelingen van
het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel XXXIX. Batavia/’s Hage:
W. Bruining & co/M. Nijhoff. 1880.
Sweeney, Amin. Karya Lengkap Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi Jilid 3: Hikayat Abdullah. Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia. 2008.
Tim Balai Bahasa Yogyakarta. Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa). II. Yogyakarta: Kanisius. 2011.
198 Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara Vol. 12 No. 2 Tahun 2021
You might also like
- Childhood Well Being 2008 UKDocument78 pagesChildhood Well Being 2008 UKGonzalo AlcalaNo ratings yet
- Kanjeng Kyai Cokro - PDFDocument29 pagesKanjeng Kyai Cokro - PDFadi_6510No ratings yet
- Sepak Terjang Bagus Rangin Dalam Surat DDocument16 pagesSepak Terjang Bagus Rangin Dalam Surat Dhi thereNo ratings yet
- Babad GresikDocument26 pagesBabad GresikAhmad Baso100% (1)
- Letters From Sultan of Perak To FrancisDocument9 pagesLetters From Sultan of Perak To FrancissahulNo ratings yet
- Ancient Javanese Recording of The PastDocument17 pagesAncient Javanese Recording of The PastPutri Ayu WulandariNo ratings yet
- A 14th Century Malay Manuscript From KerinciDocument16 pagesA 14th Century Malay Manuscript From KerinciSurinder ParmarNo ratings yet
- Sirima KiribamuneDocument12 pagesSirima Kiribamunearuna handunpathiranaNo ratings yet
- Typography and Language:The Form and Function of Post-Aallawa Scripts in Tanjung Tanah ManuscriptDocument14 pagesTypography and Language:The Form and Function of Post-Aallawa Scripts in Tanjung Tanah Manuscriptabdul azizNo ratings yet
- R. Roolvink The Variant Versions of The Malay Annals: This PDF-file Was Downloaded From HTTP://WWW - Kitlv-Journals - NLDocument25 pagesR. Roolvink The Variant Versions of The Malay Annals: This PDF-file Was Downloaded From HTTP://WWW - Kitlv-Journals - NLChaesarNo ratings yet
- The Variant Versions of The Malay AnnalsDocument24 pagesThe Variant Versions of The Malay Annalszamil100% (1)
- Ancient Literature of Sri LankaDocument8 pagesAncient Literature of Sri LankaAnonymous xifNvN50% (2)
- JMT 2022 0010Document28 pagesJMT 2022 0010zanubari hamiidahNo ratings yet
- Paranavitana 1960 PDFDocument28 pagesParanavitana 1960 PDFBhikkhu KesaraNo ratings yet
- Parameswara Islam BorschbergDocument32 pagesParameswara Islam Borschbergมา ยาNo ratings yet
- The Khmer Inscriptions of Roluos (Preah Ko and Lolei) Documents From A Transitional Period in Cambodian HistoryDocument31 pagesThe Khmer Inscriptions of Roluos (Preah Ko and Lolei) Documents From A Transitional Period in Cambodian HistorySovannarith NgyNo ratings yet
- Sumerian Literature: An OverviewDocument13 pagesSumerian Literature: An OverviewElliot Staircase100% (4)
- Dating Early Tibetan Manuscripts: A Paleographical Method (Sam Van Schaik 2013)Document17 pagesDating Early Tibetan Manuscripts: A Paleographical Method (Sam Van Schaik 2013)Naljorpa ChagmedNo ratings yet
- The Image of Prince Gebang in Babad Sutajaya ManuscriptDocument8 pagesThe Image of Prince Gebang in Babad Sutajaya ManuscriptIbrohim Maya SumarnaNo ratings yet
- Cambodia S Muslim King Khmer and Dutch S PDFDocument22 pagesCambodia S Muslim King Khmer and Dutch S PDFPhan Thanh XuânNo ratings yet
- Mediaeval Kerala-RajaDocument332 pagesMediaeval Kerala-RajaM TNo ratings yet
- Ainiakbari 00 JarrgoogDocument1,371 pagesAiniakbari 00 JarrgoogRuchika Sharma100% (1)
- The Two Kronik Tionghua of Semarang and CirebonDocument17 pagesThe Two Kronik Tionghua of Semarang and CirebonSatria jagad 15No ratings yet
- J. Schoterman An Introduction To Old Javanese Sanskrit Dictionaries and GrammarsDocument25 pagesJ. Schoterman An Introduction To Old Javanese Sanskrit Dictionaries and GrammarskangabuNo ratings yet
- Prehispanic Source Materials For The StuDocument3 pagesPrehispanic Source Materials For The StujianisaiahcagampangNo ratings yet
- ID Tinjauan Sejarah Terhadap Naskah Dan Teks Kitab Pengetahuan Bahasa Kamus Logat MDocument23 pagesID Tinjauan Sejarah Terhadap Naskah Dan Teks Kitab Pengetahuan Bahasa Kamus Logat MsayidNo ratings yet
- Palaeographical Development of The Brahmi Script in Ceylon From 3rd Century B.C To 7th Century A.D. - Fernando, P.E.EDocument20 pagesPalaeographical Development of The Brahmi Script in Ceylon From 3rd Century B.C To 7th Century A.D. - Fernando, P.E.EGirawa KandaNo ratings yet
- Dynastic History of BengalDocument409 pagesDynastic History of Bengalrivlord100% (1)
- Malay Annals: 1 Compilation HistoryDocument5 pagesMalay Annals: 1 Compilation HistoryNagentren Subramaniam100% (1)
- The I La Galigo Poetry of South Sulawesi: Pal/awaDocument10 pagesThe I La Galigo Poetry of South Sulawesi: Pal/awaAhmad SidiqNo ratings yet
- Some Reflections On Professor Paranavitana's Contribution To HistoryDocument17 pagesSome Reflections On Professor Paranavitana's Contribution To HistorydarshanieratnawalliNo ratings yet
- Introduction: Writing, Literacy, and The Origins of Japanese LiteratureDocument7 pagesIntroduction: Writing, Literacy, and The Origins of Japanese LiteratureZakaria SeloutiNo ratings yet
- Chain of King-Makasar ChronicleDocument135 pagesChain of King-Makasar ChroniclePerikanan Dan Kelautan UnilaNo ratings yet
- BP000014Document31 pagesBP000014ekaNo ratings yet
- Short Chronicles of Kings of NepalDocument6 pagesShort Chronicles of Kings of Nepalcasperwho1984No ratings yet
- Aksara Sasak, An Endangered Script and Scribal Practice: Southeast Asia, Tokyo University of Foreign Studies, 27Document12 pagesAksara Sasak, An Endangered Script and Scribal Practice: Southeast Asia, Tokyo University of Foreign Studies, 27lalu samsul jihadNo ratings yet
- Christina Tsouparopoulou Spreading Royal WordDocument18 pagesChristina Tsouparopoulou Spreading Royal WordVik DamonNo ratings yet
- On The Origin of Two Manuscripts of HIKA PDFDocument5 pagesOn The Origin of Two Manuscripts of HIKA PDFMegaOctavianyS.BachryNo ratings yet
- Looking at Palembang Through Its ManuscriptsDocument12 pagesLooking at Palembang Through Its ManuscriptsChaesarNo ratings yet
- Laguna Copperplate Inscription Apostma1992 PDFDocument22 pagesLaguna Copperplate Inscription Apostma1992 PDFMarymae De Fiesta SipinNo ratings yet
- Lineage in Siam by King Chulalongkorn (Data Paper: Number 81, Southeast, AsiaDocument15 pagesLineage in Siam by King Chulalongkorn (Data Paper: Number 81, Southeast, AsiasfsrteyddfgNo ratings yet
- Sejarah Tradisi Tulis Dalam Masyarakat Sasak LomboDocument16 pagesSejarah Tradisi Tulis Dalam Masyarakat Sasak LomboBatik KambangsriNo ratings yet
- Muhammad Tarobin: Kitab Nur Al-Salah Karya Tengku Muhammad Saleh - 1Document42 pagesMuhammad Tarobin: Kitab Nur Al-Salah Karya Tengku Muhammad Saleh - 1Muhammad AzkaNo ratings yet
- Aman Praash SharmaDocument5 pagesAman Praash Sharmajb1210134No ratings yet
- Sirima Kiribamune 1970Document17 pagesSirima Kiribamune 1970SudhammaNo ratings yet
- History of The Pallavas of KanchiDocument281 pagesHistory of The Pallavas of KanchiSharmalan Thevar100% (5)
- The Writings of K.P.H. SuryanagaraDocument29 pagesThe Writings of K.P.H. Suryanagaraverrenaldn98No ratings yet
- Mahmud Sultan of Riau Lingga Malay Tuhfat Al-NafisDocument28 pagesMahmud Sultan of Riau Lingga Malay Tuhfat Al-NafisRaistz100% (1)
- Scrisori Private HimfiDocument5 pagesScrisori Private HimfiBeckyShinigamiNo ratings yet
- Between The Lines: Realities of Scribal Life in The Sixteenth CenturyDocument18 pagesBetween The Lines: Realities of Scribal Life in The Sixteenth CenturyhalimboharilubisNo ratings yet
- Tamil Influence in Ancient Sri Lanka With Special Reference To Early Brahmi Inscriptions - All Parts - A. Veluppillai - 1979 and 1980Document29 pagesTamil Influence in Ancient Sri Lanka With Special Reference To Early Brahmi Inscriptions - All Parts - A. Veluppillai - 1979 and 1980Girawa KandaNo ratings yet
- Kerintji DocumentsDocument34 pagesKerintji DocumentsizharhafniNo ratings yet
- About Inscriptions PDFDocument52 pagesAbout Inscriptions PDFSumithra100% (1)
- 4674 14410 2 PBDocument16 pages4674 14410 2 PBAnisasulissaputriNo ratings yet
- Unsur-Unsur Historiografi Tradisional Islam Dalam TeksDocument9 pagesUnsur-Unsur Historiografi Tradisional Islam Dalam TeksTsaltsa Halimatussadiyah Wulandari MuttaqienNo ratings yet
- Was Hangul Sole Invention of Sejong (Yeon)Document20 pagesWas Hangul Sole Invention of Sejong (Yeon)Blue-Oh MeloNo ratings yet
- s0035869x00053843 PDFDocument2 pagess0035869x00053843 PDFanjanaNo ratings yet
- The Medieval History Journal Volume 9 Issue 2 2006 (Doi 10.1177/097194580600900206) Sarkar, N. - 'The Voice of Mahmud' - The Hero in Ziya Barani's Fatawa-I JahandariDocument30 pagesThe Medieval History Journal Volume 9 Issue 2 2006 (Doi 10.1177/097194580600900206) Sarkar, N. - 'The Voice of Mahmud' - The Hero in Ziya Barani's Fatawa-I JahandariSabah Mushtaq100% (1)
- Notes On The Lontara Bugis Indonesia MalayDocument14 pagesNotes On The Lontara Bugis Indonesia MalayRaistz100% (2)
- Ulama Melayu Pada Abad XXDocument29 pagesUlama Melayu Pada Abad XXYadi KartonoNo ratings yet
- L0062-19 - Deskripsi Karakteristik Individu TransmigrasiDocument11 pagesL0062-19 - Deskripsi Karakteristik Individu TransmigrasiYadi KartonoNo ratings yet
- ArkeisDocument1 pageArkeisYadi KartonoNo ratings yet
- Arsip VOC S HasanahDocument11 pagesArsip VOC S HasanahYadi KartonoNo ratings yet
- How To Pray For 30 MinutesDocument1 pageHow To Pray For 30 MinutesncubenonieNo ratings yet
- Heirs of Franco vs. Sps. Gonzales, G.R. No. 159709Document17 pagesHeirs of Franco vs. Sps. Gonzales, G.R. No. 159709joluwcarNo ratings yet
- Dhananjay ReportDocument28 pagesDhananjay ReportManojitDebroyNo ratings yet
- Sterling and Wilson's Annual ReportDocument8 pagesSterling and Wilson's Annual ReportAmar PandeyNo ratings yet
- Adaza vs. Pacana (G.R. No. L-68159 - March 18, 1985)Document1 pageAdaza vs. Pacana (G.R. No. L-68159 - March 18, 1985)Lecdiee Nhojiezz Tacissea SalnackyiNo ratings yet
- Alp en Lie BeDocument10 pagesAlp en Lie BevimalnandiNo ratings yet
- Olimpiada VII VIIIDocument8 pagesOlimpiada VII VIIIMihaela Oprea100% (1)
- Com Law 1 IntroDocument70 pagesCom Law 1 IntrosejalNo ratings yet
- Biography Sayuti MelikDocument2 pagesBiography Sayuti Melikraymufalayli sachdriNo ratings yet
- Dealers Perception Objectives of The StatementDocument3 pagesDealers Perception Objectives of The StatementBala Murugan MNo ratings yet
- Sociolinguistics #1Document19 pagesSociolinguistics #1Ikram100% (1)
- RPMS SY 2021-2022: Teacher Reflection Form (TRF)Document3 pagesRPMS SY 2021-2022: Teacher Reflection Form (TRF)Badeth AblaoNo ratings yet
- Writer's Survival GuideDocument12 pagesWriter's Survival GuidejoburkholderNo ratings yet
- Rav Moshe Shapiro - Discussion Daas TorahDocument11 pagesRav Moshe Shapiro - Discussion Daas Torahyadmoshe100% (4)
- Introduction To The European Union: Scenes From Europe at The End of World War IIDocument24 pagesIntroduction To The European Union: Scenes From Europe at The End of World War IIPankaj PalNo ratings yet
- Judical InterpretationDocument15 pagesJudical InterpretationShivaniNo ratings yet
- Vet MedDocument1 pageVet MedSirwan SalmanNo ratings yet
- Long Day's Journey Into Night - 240511 - 081949Document8 pagesLong Day's Journey Into Night - 240511 - 081949drarrynightmareNo ratings yet
- Text Di Bawah Ini Digunakan Untuk Menjawab Nomor 1 Dan 2.: Rahmat and Wati JumintenDocument3 pagesText Di Bawah Ini Digunakan Untuk Menjawab Nomor 1 Dan 2.: Rahmat and Wati JumintenKiddy Care TegalNo ratings yet
- Teaching and Research StatementsDocument20 pagesTeaching and Research StatementsMónicaSalazarNo ratings yet
- Opposition - Declaration of NullityDocument3 pagesOpposition - Declaration of NullityJay ArNo ratings yet
- Pocket Guide Facing Down A Civil WarDocument104 pagesPocket Guide Facing Down A Civil Warsequoya.snowNo ratings yet
- Mikhail Gorbachev 58Document6 pagesMikhail Gorbachev 58IniAlvinNo ratings yet
- Language and Intercultural CommunicationDocument13 pagesLanguage and Intercultural Communicationacademic11.thamesukNo ratings yet
- People Vs Perfecto, 43 Phil 887Document10 pagesPeople Vs Perfecto, 43 Phil 887invictusincNo ratings yet
- BGDT20048493 Report Number:: ITS Labtest Bangladesh LTDDocument4 pagesBGDT20048493 Report Number:: ITS Labtest Bangladesh LTDanwar sadatNo ratings yet
- Amendment of By-Laws For Members (By-Laws of Institute of Engineers of The Philippines)Document17 pagesAmendment of By-Laws For Members (By-Laws of Institute of Engineers of The Philippines)meecheekohNo ratings yet
- 334259626Document14 pages334259626dasarirevanth2002No ratings yet
- Girotra Vinay Civil-Military RelationsDocument11 pagesGirotra Vinay Civil-Military Relationsvkgirotra100% (5)