ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
Kronotop Kontra Politik dan Visualitas Korban
dalam Film Dokumenter: Kajian Antropologi Media
Aryo Danusiri
Departemen Antropologi, Universitas Indonesia dan Harvard University
danusiri@gmail.com
Abstract
This article is my retrospective account on the making of one of my testimonial documentaries,
“Kameng Gampoeng Nyang Keunong Geulawa” (The Village Goat that Takes the Beating, 1999)
which was commissioned by a human rights-defender NGO based in Jakarta. The aim was to offer
critical views on the Aceh conflict to the Indonesian public. By using chronotopes (Bakhtin, 1981) as
the analytical tool, I delineate the way the Indonesian state and its military constituted a dominant
view of Aceh as the Other by applying a semiotic model of authoritarian nationalism that circulated
in the public sphere. As the counter-politics, I developed particular testimony chronotopes as a
strategy to capture victims’ points of view as embodied experience. In my reflection, I argue that
instead of producing a complex visuality of the Aceh actors as human beings, my portrayal of the
victims had taken on a sustained oppressor-victim binary opposition view which framed victims as
the articulation of singular experience. This study contributes to the emerging interest in media
anthropology and the study of non-mainstream film genres and independent cinema works.
Keywords: Aceh, Chronotopes, Cinema, Counter-politics, Documentary of Testimony, Independent,
Nationalism-Separatism
Ketika menyampaikan ulasannya mengenai
situasi Asia Tenggara dan konsep kebudayaan
sebagai alat analisis antropologi pada tahun
1999, Mary Steedly menulis bahwa wilayah
ini berada dalam situasi tidak pasti karena
perubahan yang terjadi dalam skala besar dan
cepat, serta berakhir dengan krisis
multidimensional pada akhir dekade ‘90-an.
Steedly melihat bahwa dalam kajian mereka,
banyak ahli Asia Tenggara tidak lagi berfokus
pada kebudayaan sebagai konsep untuk
mendefinisikan
entitas
sosial,
tetapi
kebudayaan sebagai alat politik negara.
Operasi kekuasaan tersebut dapat dicermati
dalam tiga situs: gender, politik kebudayaan,
dan praktik-praktik kekerasan (Steedly,
1999).
Salah satu praktik yang tidak kalah
penting sejak dekade ‘90-an adalah
perkembangan media massa. Perhatian pada
media menjadi penting tidak saja karena
proses privatisasi media arus utama dimulai di
era ini, tetapi juga karena negara dan sektor
privat menggunakan media massa sebagai alat
untuk melanggengkan kekuasaan dan
mendisiplinkan masyarakat lewat berbagai
jenis tayangan yang mereka produksi. Di era
Reformasi (masa pasca-kejatuhan Suharto
1998) kebebasan media menjadi indeks dari
Indonesia baru yang demokratis. Media
mengalami
perkembangan
yang
memungkinkannya menjadi teknologi untuk
mengonstitusi
formasi
sosial-politik
alternatif. “Memberdayakan ruang publik”
136
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
adalah kata kunci yang bersirkulasi dalam
berbagai program pelatihan, penerbitan,
advokasi demokratisasi, dan desentralisasi
media (mulai dari media cetak hingga
elektronik) yang didanai oleh berbagai agensi
dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)
international.
Fokus dari artikel ini adalah refleksi
saya atas proses pembuatan dokumenter
Kameng Gampoeng yang Keunong Geulawa
(Kambing Kampung Yang Kenal Pukul) yang
diproduksi tahun 1999. Dokumenter tersebut
menyajikan testimoni korban pelanggaran hak
asasi manusia (HAM) selama konflik
bersenjata di Aceh. Topik ini memiliki arti
penting dalam beberapa hal. Pertama,
dokumenter ini merupakan bagian dari
maraknya penggunaan video sebagai media
kampanye gerakan sosial. Dengan kata lain,
merupakan
satu
bentuk
program
pemberdayaan media era Reformasi. Sampai
saat ini sektor pembangunan (development
sector)
dan
organisasi-organisasi
humanitarian masih memegang peranan
penting
dalam
produksi
video-video
dokumenter. Video dokumenter testimoni
menjadi
instrumen
bagi
kerja-kerja
pembelaan HAM dan gerakan sosial di tingkat
global karena dianggap ampuh untuk
merepresentasikan korban kekerasan dan
subjek-subjek marginal lainnya (petani, orang
miskin, dan lain sebagainya).
Kedua, genre testimoni adalah genre
paling populer dalam produksi video
1
dokumenter di Indonesia. Genre ini tidak saja
mendominasi dokumenter produksi LSMLSM, tetapi juga menjadi pilihan bentuk
ekspresif dari sineas-sineas senior di
Indonesia (Hanan, 2012). Ketiga, dalam
situasi
“kekacauan
pasca-kolonial”
(postcolonial disorders) (Good, Hyde, Pinto,
& Good, 2008), yaitu situasi kontradiktif yang
dialami oleh negara maupun warganya
akibat—salah
satunya—pengalaman
kolonialisme,
dokumenter
memainkan
peranannya di Indonesia. Konflik Aceh
senantiasa terkait dengan sejarah masa
kolonial dan memperlihatkan negara dalam
kondisinya yang kontradiktif: kuat sekaligus
rapuh. Bagaimana kemudian dokumenter
sebagai media kontra-politik memainkan
perannya dalam proses demokratisasi pascakolonial?
Video Kameng Gampoeng masih
terus diputar di ruang-ruang publik baik di
Indonesia maupun di kancah internasional.1
Terakhir kali video ini diputar di program
“Kreativitas Bercerita mengenai Represi Hak
Asasi” yang dikuratori oleh Jonathan
Manullang.2 Saya menulis artikel ini dengan
tujuan untuk berbagi pengalaman dan
pandangan atas problem representasi korban
dalam dokumenter testimoni. Saya sebut
sebagai refleksi karena tulisan ini adalah
campuran antara ingatan saya tentang proses
pembuatan dan proses sosial politik yang
melingkupinya dengan pembahasan saya
mengenai konteks tema dan genre
Pada bulan Desember 2018, saya menjadi salah juri kompetisi dokumenter pendek Festival Film Dokumenter di
Yogyakarta, yaitu festival dokumenter tertua di Indonesia dan Asia Tenggara. Dari lima film dokumenter finalis yang
kami nilai, tiga diantaranya menggunakan moda testimoni di dalamnya dan satu dokumenter yang terlihat jelas sebagai
dokumenter testimoni.
2
Video Kameng Gampoeng bisa bersirkulasi dengan baik diberbagai ruang publik. Video ini terseleksi untuk
ditayangkan pada Jakarta International Film Festival pertama pada tahun 2000 dan Amnesty Film Festival di
Amsterdam, Belanda pada tahun 2001. Terkahir video ini diputar di konferensi Sign of Crisis New York University
(2007) dan Arkipel Film Festival (2015) di Jakarta.
137
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
dokumenter. Selain itu, saya juga
melengkapinya dengan literatur-literatur baru
yang relevan. Hingga saat ini memang sedikit
tulisan
akademis
mengenai
praktik
dokumenter sosial-politik di Indonesia.
Tulisan ini sendiri dapat memberikan
kontribusi dalam konteks perdebatan
metodologis terkait dokumenter, terutama
dalam proses produksinya.
Dokumenter dalam Tinjauan Antropologi
Media
Antropologi
media
pada
awalnya
memusatkan perhatian pada media sebagai
produk nasional dan meneliti bagaimana
media
merepresentasikan
kebudayaan
nasional. Pada periode ini, kebudayaan
nasional dipahami sebagai kesatuan maknamakna yang solid yang entah bekerja secara
sistemik atau disiplinaristik membentuk
subjek warga negara lewat proses-proses
transmisi media teknologi. Karya-karya
antropologi media ini umumnya berfokus
pada media-media arus utama, seperti film,
televisi, industri musik, atau koran dan
majalah.
Perubahan yang dihasilkan oleh
teknologi digital mendorong para antropolog
untuk berpikir ulang mengenai supremasi
teori kebudayaan nasional. Perubahan ini juga
membuka periode baru dalam melihat media
sebagai proses mediasi yang beruntun
(concantenative). Kata kunci teknologi digital
adalah
partisipasi,
yang
menjadikan
kebudayaan nasional sebagai kerja yang takpernah-selesai dalam ruang-ruang bersama.
Komunikasi lewat media bukan lagi sekadar
praktik “transmisi” ataupun “ritualistik”
(Carey, 1992) dari kebudayaan nasional.
Namun, kebudayaan nasional menjadi
peristiwa media itu sendiri. Konstitusinya
terfragmentasi karena dihasilkan lewat kerjakerja mediasi dari media teknologi yang
partisipatif. Dalam pendekatan kontemporer
ini, perhatian antropolog telah dialihkan pada
aspek-aspek yang sebelumnya diabaikan,
yakni pada media-media non-arus utama,
serta pada aspek material dan teknologi dari
media. Brian Larkin (2008), misalnya,
memilih meneliti bioskop ketimbang film;
Mary Steedly (2013) memilih “B movies”
ketimbang film-film arus utama; Patricia
Spyer (2002) melihat media skala kecil/taktis
(small scale/tactical media) ketimbang media
massa. Sejalan dengan kecenderungan
tersebut, dalam artikel ini saya berfokus pada
film dokumenter sebagai medium sinema
non-industrial yang sering diabaikan, baik
dalam sirkulasi jaringan formal maupun
dalam kajian film Indonesia.
Bila kita bicara mengenai genre dalam
sinema dokumenter, maka penting untuk
menimbang keluhan Stella Bruzzi (2006),
bahwa
genre
dalam
dokumenter
sesungguhnya membatasi perkembangan
dokumenter itu sendiri, alih-alih mengadopsi
inovasi-inovasi yang terjadi. Bruzzi menyasar
moda-moda (atau genre) dalam dokumenter
yang diciptakan oleh Bill Nichols di tahun
1980-an sebagai persoalan karena sudah
dipercaya bukan sebagai “salah satu cara”
dalam membuat dokumenter, namun “satusatunya cara” (Bruzzi, 2006: 3). Bruzzi
menyarankan interogasi terhadap genre-genre
dokumenter
agar
bisa
menangkap
heterogenitas
perkembangan
medium
sinematik ini. Antropolog media, W. J. T.
Mitchell (2005), menyarankan agar proses
menginterogasi imaji sebaiknya tidak
138
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
dilakukan dengan memperkirakan kuasa imaji
dalam politik secara berlebihan, namun
sebaliknya, memperlakukan imaji sebagai
subjek subaltern dan mulai dengan
pertanyaan agar imaji dapat bersuara. Dengan
sikap bertanya inilah kita bisa meninggalkan
sikap apriori terhadap kekuatan imaji dan
mulai menggali posibilitas dan potensialitas
dari imaji (Mitchell, 2005: 34).
Dalam artikel ini saya akan berbagi
mengenai pergulatan saya dengan visibilitas
genre dokumenter testimoni, yaitu formasi
hierarkis antara the visible (yang-terlihat) dan
the invisible (yang-tak-terlihat). Formasi
tersebut tidak inheren melekat pada genre
testimoni
sebagai
instrumen,
tetapi
dikonstruksi dalam negosiasinya dengan
konteks sosial politik yang melingkupi
produksi dokumenter itu sendiri. Namun
demikian, sebagai proses komunikatif,
pembahasan pembuatan dokumenter ini tidak
fokus pada aspek politiknya (aspek
bagaimana
pesan/makna
yang
baku
ditransmisi kepada penonton), melainkan
aspek pada “puitik”-nya (Carey, 1992). Aspek
puitik terkait dengan proses mempraktikkan
genre sebagai proyek penyampaian berulangulang (iterability) (Derrida, 1972) ke dalam
konteks baru untuk bisa mengonstruksi makna
yang baru. Oleh karena itu, mengikuti Bakhtin
(1981), genre di sini saya pahami sebagai
kronotop (chronotopes), yaitu model semiotik
hubungan antara ruang dan waktu yang
menopang representasi.
Efikasi sebuah karya dokumenter
ditentukan oleh kemampuan sang pembuat
karya untuk mengonfigurasi beragam
kronotop
dalam
berbagai
modalitas
keterhubungan: kesejajaran, perbandingan,
pertentangan dan lain sebagainya (Alatas,
139
2016; Stasch, 2011). Kronotop memproduksi
subjek karena “[t]he image of man is always
instrically chronotopic” (Bakhtin, Wright, &
Holquist, 1981: 85). Karakter lain dari
kronotop
ialah
konstruksinya
selalu
dipraktikkan
melalui
kerangka
kerja
partisipasi
(participation
frameworks),
apakah itu dalam “dunia penulis” atau “dunia
pembaca dan pendengar” (Bakhtin, Wright, &
Holquist, 1981: 257). Dalam mengonstruksi
teks audio-visualnya, seorang sineas akan
mengantisipasi
penontonnya
sehingga
kronotop dalam teks selalu berada dalam
hubungan “dialogis” (Bakhtin, Wright, &
Holquist, 1981: 256) dengan kronotop
publik—atau yang disebut oleh Agha (2007)
sebagai mass-mediated chronotopes—yang
menjadi konteks komunikasinya.
Produksi dokumenter merupakan
proses sosial (Bakhtin, Wright, & Holquist,
1981). Artinya, proses merekonstruksi
kronotop dilakukan lewat pembangunan
hubungan di antara para aktor (publik, nonpublik, dan sub-publik) yang diacu dan
terlibat dalam proses produksi dengan
kronotop-kronotop
dalam
kerangka
partisipasi masing-masing. Di ruang publik,
Aceh direpresentasikan sebagai liyan (the
other) di bawah dominasi kronotop
“nasionalisme otoritarian” yang diproduksi
oleh negara dan disirkulasi oleh media massa.
Kronotop dominan ini menciptakan jarak
dengan para korban di Aceh sebagai sosok
pasif yang sekadar bagian dari massa atau
kerumunan yang diproduksi oleh Order Baru.
Di ruang publik juga, pemerintah dan tentara
Indonesia merepresentasikan orang-orang
Aceh yang terlibat dalam konflik bersenjata
dengan kronotop mereka sebagai “gerakan
separatis”. Dengan demikian, mereka
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
ditampilkan sebagai “pengacau” yang berada
di luar waktu linear pembangunan bangsa,
sehingga harus ditertibkan. Kronotop kontrapolitiiknya berupa kronotop “reformasi” yang
mendefinisikan waktu saat ini sebagai periode
baru yang demokratis dan berbeda dari
periode Orde Baru yang otoriter. Kedua
kronotop ini berada dalam hubungan
kontradiktif dan saling membatalkan. Kedua
kronotop
ini—kronotop
nasionalisme
otoritarian dan kronotop reformasi—
mendefinisikan korban dengan cara berbeda
dan menjadi pijakan saya dalam membuat
video Kameng Gampoeng. Proses pembuatan
video kemudian mengarahkan saya untuk
memikirkan, apakah mungkin memahami
korban sebagai subjek politik di luar kedua
kronotop yang bertentangan ini?
Kronotop Dominan: Pra-Produksi
Seperti yang sudah saya sebutkan
sebelumnya, proses pembuatan dokumenter
bukanlah proses terisolasi, melainkan proses
sosial yang melibatkan berbagai aktor sosial
untuk menghasilkan teks yang bermakna
sesuai
dengan
karakter
medium
representasinya. Mengonstruksi kronotop
adalah bagian dari proses pembuatan tersebut
yang pada gilirannya menjadi pedoman dalam
merepresentasikan secara koheren wakturuang dan subjek dari momen sejarah tertentu
(Bakhtin et al., 1981: 243). Upaya
merepresentasikan Aceh dan para korban
DOM tergantung pada kronotop-kronotop
mengenai Aceh yang beredar di ranah publik,
yaitu kronotop-kronotop yang dimediasi oleh
media massa. Oleh karena itu, dokumenter
3
yang dihasilkan adalah artikulasi dari matriks
kronotop-kronotop yang bersifat publik yang
dikonfigurasi lewat produksi dokumenter
tersebut.
Aceh di tahun 1999 diliputi krisis
politik dan kekerasan militer yang bertautan
dengan reformasi politik yang baru saja
terjadi di Indonesia. Dimotori oleh Gerakan
Aceh Merdeka (GAM), suara yang terdengar
dari Aceh pun menggaungkan semangat untuk
merdeka sebagai negara berdaulat yang
terpisah dari Republik Indonesia. Saat itu,
teriakan merdeka tidak saja dilantangkan dari
Aceh di ujung barat Indonesia, tapi juga dari
Papua di ujung timur. Berawal dari tuntutan
rakyat Aceh agar pemberlakuan DOM
(Daerah Operasi Militer) segera dicabut, pada
6 Agustus 1998 Panglima ABRI Jenderal TNI
Wiranto mencabut status DOM di Aceh. Akan
tetapi, sehari setelah itu ratusan tentara nonorganik dikirim dari Medan dan Jakarta ke
Aceh dengan alasan untuk mengatasi “kaum
separatis” yang semakin bergerak dan
berkembang (Kompas, 3 Agustus 1999).
Selama periode tersebut, berita-berita
di media massa nasional cetak maupun
elektronik dipenuhi dengan kisah-kisah dalam
konflik politik Aceh. RCTI (Rajawali Citra
Televisi Indonesia) menjadi stasiun TV
swasta yang gencar memberitakan konflik
Aceh dengan materi-materi visual yang
eksklusif. Hal ini bisa terjadi karena
departemen pemberitaannya (yang terkenal
dengan nama program berita “Seputar
Indonesia”) memiliki koresponden khusus di
Lhokseumawe, Aceh, yaitu Umar HN,
seorang wartawan senior yang sebelumnya
bekerja untuk harian Waspada di Medan.3
Chik Rini, “Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” https://www.pantau.or.id/?/=d/161 diakses 1 Maret 2019
140
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
Rupanya tidak hanya untuk RCTI saja, Umar
juga memasok rekaman-rekaman berita untuk
kantor berita asing. Rekaman-rekaman yang
diproduksi oleh Umar inilah yang kemudian
menjadi dasar saya dalam proyek pembuatan
film dokumenter pertama saya mengenai
Aceh.
Pada bulan Juli 1999, seorang kawan
memberi tahu saya bahwa ELSAM (Lembaga
Studi Advokasi Masyarakat) yang bergerak di
bidang HAM (hak asasi manusia) dan
berkantor di Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
tengah mencari seorang videografer untuk
proyek dokumenter kampanye mereka. Saya
kemudian bertemu dengan direkturnya, Ifdhal
Kasim, yang menjelaskan bahwa mereka
merencanakan pembuatan video kampanye
mengenai berbagai pelanggaran HAM di
Aceh yang dilakukan oleh tentara Indonesia.
Bahan yang telah mereka sediakan meliputi
beberapa rekaman video seputar pelanggaran
HAM yang diproduksi oleh Umar HN.
Tragedi Simpang KKA, Kuburan Massal
Beutong, dan Penyerangan Kampung
Kandang adalah rekaman-rekaman utama
dalam koleksi tersebut. Setelah dijelaskan
lebih detail mengenai spesifikasi video yang
mereka inginkan dan rincian pembiayaan
yang telah mereka persiapkan, saya pun
memikirkan lebih lanjut produksi video
kampanye tersebut. Pada dasarnya, ELSAM
ingin membuat sebuah video kampanye untuk
menanggapi kejadian-kejadian krisis politik
di Aceh dan memberikan pendidikan publik
mengenai pelanggaran HAM. Diharapkan
video dokumenter kampanye yang dihasilkan
berdurasi pendek dan cocok sebagai pemantik
diskusi dalam kegiatan-kegiatan perencanaan
program kampanye.
141
Keesokan harinya, lewat telepon saya
meminta waktu untuk bertemu lagi dengan
Ifdhal Kasim. Dalam pertemuan tersebut, saya
menjelaskan tanggapan saya terhadap desain
video kampanye mereka. Pertama, rekaman
berita dari Umar HN hanya berfokus pada
peristiwa-peristiwa besar pelanggaran HAM,
sehingga upaya mengembangkan rekamanrekaman tersebut menjadi sebuah video
dokumenter yang dapat memberikan
perspektif kritis di luar perspektif dominan
yang direproduksi media massa nasional
menjadi terbatas. Kedua, oleh karenanya, saya
menawarkan pendekatan alternatif, yaitu
dengan melakukan wawancara langsung
dengan para korban kekerasan. Penawaran
saya berdasarkan pendekatan etnografis yang
mengedepankan pertemuan tatap muka
dengan informan dan mengalami secara
langsung situasi mencekam yang terjadi. Saya
menggunakan istilah jurnalistik “wawancara”
yang saya anggap cukup populer untuk
mengartikulasi bahwa bentuk usulan video
yang akan saya buat melampaui video esai
politik yang awalnya direncanakan oleh
ELSAM. Ketiga, saya sampaikan bahwa telah
tersedia teknologi baru di dunia sinema
berupa teknologi digital. Dengan anggaran
relatif terjangkau, teknologi ini dapat
menghasilkan kualitas tinggi yang layak
untuk tontonan publik. Dengan nada persuasif
saya sampaikan bahwa dengan menambahkan
sedikit dana produksi yang telah dianggarkan,
ELSAM bisa mendapatkan video dokumenter
dengan mutu muatan yang lebih istimewa dan
kualitas sinema yang prima.
Desain video dokumenter yang saya
tawarkan adalah artikulasi dari interseksi
antara kronotop nasionalisme otoritarian
tentang Aceh dan kronotop reformasi tentang
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
Indonesia baru. Secara politik, kronotop
otoritarian tentang Aceh adalah perspektif
dominan yang bersirkulasi di ruang-ruang
publik.
Model
waktu-ruang
ini
mengutamakan imajinasi keutuhan wilayah
Republik Indonesia sebagai cara memahami
konflik Aceh, yaitu meletakkan TNI (Tentara
Nasional Indonesia) sebagai subjek bersenjata
yang bertujuan mempertahankan keteraturan
(order), sedangkan GAM (Gerakan Aceh
Merdeka) sebagai pihak yang menciptakan
kekacauan (disorder) sehingga layak untuk
diperangi. Di lain pihak, GAM juga
menggunakan logika yang serupa untuk
mengonstruksi eksistensi Aceh Merdeka
sebagai entitas etno-nasional yang jelas. Oleh
karena itu, mereka menyuarakan dirinya
sebagai sosok yang membebaskan rakyat
Aceh dari tekanan dan eksploitasi Indonesia
yang kolonialis, kejam, dan tamak (lihat AlChaidar, Ahmad, & Dinamika, 1999).
TNI sebagai bagian dari RI
mengklaim sebagai entitas yang sah,
demokratis, dan representasi dari entitas
bangsa Indonesia yang homogen. Kronotop
nasionalisme otoritarian sebagai varian dari
kronotop nasionalisme memiliki karakter
yang sama dalam chronotpolitics-nya, yaitu
pengaturan komunitas yang disebut “bangsa”
hanya dapat dimungkinkan dalam sebuah
entitas kebangsaan yang baru bila
keberagamannya disatukan dalam sebuah
linearitas
waktu
yang
baru—dalam
terminologi Anderson (2006), politik waktu
ini melibatkan “waktu kosong yang
homogeny” (homogenous empty time).
Kronotop seperti ini menghasilkan dua subjek
yang saling bertentangan: penindak dan
perusuh. Ketimbang mengakui eksistensi
GAM sebagai musuh yang berdaulat, TNI
menyebut dirinya sebagai Pasukan Penindak
Rusuh Massa (PPRM) dan menjadikan GAM
sebagai sosok liyan (the other) dengan
sebutan GBPK (Gerombolan Bersenjata
Pengacau Keamanan) (Kompas, 16 Juli 1999).
Adapun GAM melakukan hal serupa dengan
menggunakan metafora dan alegori sejarah,
seperti hikayat perang sabil, untuk
menstrukturkan bahwa inilah momen untuk
bangkit dan melawan kaphe (penjajah).
Perang dalam sejarahnya selalu merupakan
teater kekerasan yang digelar di ruang publik
dan secara semiotik membutuhkan penandaan
oposisi biner sebagai dasar lakonnya.
Kronotop
reformasi
merupakan
konsepsi yang melihat waktu setelah
kejatuhan Suharto sebagai waktu yang
berbeda dari sebelumnya. Ada patahan antara
waktu Orde Baru dan pasca-Orde Baru.
Dalam kata pengantar salah buku seri
Transitional Justice (Bronkhorst, 2002),
ELSAM memberikan kerangka waktu
terhadap makna penerbitan buku tersebut:
“SETELAH lebih 32 tahun hidup di bawah
kekuasaan pemerintahan yang otoriter dengan
dukungan ideologi militer yang menindas, dan
kembali memasuki era keterbukaan, reformasi
dan demokrasi, bangsa Indonesia sepertinya tidak
peduli dengan apa yang terjadi pada masa lalu.
Bahkan perbincangan sistematis tentang upayaupaya penyelesaian hukum dan politis belum
menjadi agenda utama banyak kalangan, baik
DPR maupun pemerintah.”
Waktu reformasi bukanlah waktu bagi
otoritarianisme,
tetapi
waktu
bagi
keterbukaan dan demokrasi. Oleh karena
kronotop adalah kategori, maka ELSAM
mengadvokasi bahwa pelanggaran HAM
masa lalu seharusnya menjadi elemen penting
dari kategori waktu-ruang reformasi, seperti
142
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
halnya kebebasan berbicara atau supremasi
sipil juga menjadi bagian dari era ini. Subjek
yang diproduksi oleh kronotop ini adalah
“korban” dan advokasi korban adalah penting
mengingat dalam kronotop otoritarian, korban
dianggap sebagai subjek yang tak-terlihat.
Maka, langkah awal dalam pemulihan hakhak korban adalah bagaimana mereka bisa
memberikan kesaksian sehingga dapat
mengungkap ingatan traumatik mereka
sebelum proses reparasi diberikan (Kasim,
2003: 123).
Pembuatan
dokumenter
adalah
aktivitas semiotik yang melibatkan kronotop
beserta proses konstruksi konfigurasi
multikronotop. Aktivitas ini selalu terjadi
dalam kerangka kerja partisipan (Agha, 2007:
322). Pada saat itu, apa yang ada di hadapan
saya adalah konstitusi korban dalam
konstelasi dua kronotop yang saling
bertentangan.
ELSAM
menginginkan
kronotop reformasinya tentang korban
diekspresikan melalui film dokumenter
dengan menggunakan news footages dari
televisi. Saya menolak hal ini karena menurut
kerangka kerja semiotik saya, film adalah
bagian dari kronotop reformasi yang
seharusnya menjadi artikulasi baru yang
independen di luar media arus utama,
termasuk TV. Reformasi sesungguhnya
membuka ruang baru bagi para pembuat film
untuk bisa membuat film di luar logika
representasi yang direproduksi oleh media
kapitalistik. Dalam kerangka kerja partisipasi
ini, saya membangun asosiasi semiotik antara
kronotop reformasi dari ELSAM dengan
kronotop film independen, sehingga bisa
memberikan makna baru mengenai korban
sebagai alternatif penggambaran korban oleh
143
berita-berita televisi (yang banyak mengikuti
kronotop nasionalisme milik negara).
Secara teknologis, teknologi video
digital berkembang pesat di akhir 1990-an dan
mulai menjadi medium sinematik yang sah.
Lebih dari sekadar teknologi “batu pijakan”,
teknologi ini memberikan perspektif baru
dalam dunia sinema. Istilah film independen
ketika itu sangatlah lekat dengan teknologi
video digital ini karena membuka peluang
bagi para sineas untuk bisa menjelajah
wilayah estetika dan tema baru secara
mandiri, karena secara ekonomis lebih
terjangkau. Dogme 95 Vow of Chastity yang
dimotori oleh sekelompok sineas Denmark
adalah contoh gerakan sinema baru yang
merayakan keabsahan video digital sebagai
medium ekspresi sinematik dan dihargai oleh
komunitas sinema dunia. Mereka membuat
manifesto yang menjelaskan aturan-aturan
khas dalam pembuatan film. Inti dari
manifesto tersebut adalah meminimalkan
artifisialitas dalam pembuatan film, seperti
melarang penggunaan properti dan set
tambahan di lokasi, hanya menggunakan
lampu yang tersedia secara alami di lokasi,
hingga kamera merekam adegan secara apa
adanya dengan gaya hand-held. Sekilas
seperangkat aturan tersebut seperti metodemetode dalam gaya dokumenter observasi
yang mengutamakan perekaman pengalaman
ketubuhan subjek dalam proses-proses sosial
politik.
Dalam
konteks
Indonesia,
penyelenggaraan
Festival
Film-Video
Independen Indonesia pada tahun 1999
menekankan kesejajaran medium film dan
video sebagai medium sinematis dengan
meninggalkan perspektif lama yang melihat
film dan video dalam hubungannya yang
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
hierarkis.4 Dalam konteks wacana video
etnografi, harapan untuk bisa mengungkap
kemungkinan-kemungkinan
baru
juga
disampirkan pada teknologi video digital.
Selain memberikan kebebasan secara
finansial dalam produksi video etnografi,
kamera video digital juga bisa memberikan
perspektif baru dalam mengonstruksi
keintiman antara antropolog dan subjeknya
(Bakhtin, Wright, & Holquist, 1981: 85).
Kamera video digital memberikan mobilitas
baru bagi antropolog untuk menjelajah
kemungkinan baru dalam ranah metodologis
maupun praktis.
Membuat film dokumenter yang
berfokus pada korban konflik bersenjata
sebagai subjek adalah reaksi terhadap
kronotop nasionalisme militeristik yang saya
jelaskan di atas. Sikap untuk tidak berpihak
pada salah satu entitas yang bertikai, tetapi
berpihak pada korban yang terjebak dalam
konflik, adalah suatu keniscayaan dalam
advokasi politik kritis. Keberpihakan terhadap
korban adalah perspektif yang pada saat itu
disirkulasikan oleh kalangan LSM (lembaga
swadaya masyarakat) serta aktivis politik dan
HAM, termasuk ELSAM. “Korban” menjadi
kategori politik yang memiliki daya kritis
baru pasca-reformasi. Visibilitas korban tidak
saja hadir secara diskursif, tetapi juga secara
institusional lewat pembentukan berbagai
“tim pencari fakta”.
Pada tanggal 23 September 1999,
beberapa hari sebelum saya berangkat untuk
merekam gambar di Aceh, Komisi Nasional
Perempuan
(Komnas
Perempuan)
menyelenggarakan diskusi publik dengan
judul “Dimensi Kemanusiaan dalam Konflik
Bersenjata: Landasan Hukum Internasional”.
Poin-poin yang disampaikan adalah soal
keberpihakan pada korban sebagai tindakan
imperatif karena mereka dipahami sebagai
pihak yang tak berdaya. Dalam konteks
memperhatikan dimensi kemanusiaan dalam
konflik bersenjata, Anne-Sophie Gindroz dari
International Committee of the Red Cross
menegaskan
bahwa
tugas
lembaga
kemanusiaan adalah memastikan kebutuhan
dasar para korban terpenuhi tanpa terlibat
secara politik dalam pertikaian. Korban selalu
dilupakan dalam pertikaian politik, sehingga
advokasi terhadap keberadaan mereka
menjadi penting, seperti dikatakan dalam
salah satu makalah yang dipresentasikan,
“Yang menjadi perhatian kita sekarang ini
adalah jatuhnya korban dari mereka yang
lemah dan tidak berdaya membela dirinya
sendiri. Dalam waktu yang cukup lama
korban-korban tersebut dipandang sekadar
sebagai catatan kaki….” (Bahar, 1999: 1).
Pada penutup makalahnya, Bahar (1999)
mengingatkan
pentingnya
membela
kelompok terlemah dalam pertikaian
bersenjata, yaitu perempuan, orang tua, dan
anak-anak.
Salah satu ikon yang banyak diungkap
dan dijadikan fokus dalam gugatan para
aktivis dan lembaga pembela HAM dalam
kasus konflik Aceh adalah “gampoeng
janda”. Istilah ini merujuk kepada kampung
yang penghuninya dominan kaum perempuan
dan anak-anak karena para lelaki dan suami
pergi meninggalkan kampung, baik secara
paksa maupun atas kemauan sendiri, terkait
4
Misalnya saja, pemerintah secara resmi menyelenggarakan dua festival film berbeda untuk dua medium berbeda
yaitu Festival Film Indonesian (FFI) dan Festival Sinetron Indonesia (FSI) yang memberikan supremasi lebih kepada
FFI sebagai festival utama.
144
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
dengan operasi militer. Subjek laki-laki
adalah subjek yang paling rentan menjadi
sasaran militer untuk diculik dan diinterogasi
dengan kekerasan karena ditengarai memiliki
hubungan langsung atau tidak langsung
dengan “para pengacau”. Ada banyak
kampung yang dapat diidentifikasi sebagai
gampoeng janda, salah satu yang paling
populer ialah Kampung Cot Keng yang
terletak di Kabupaten Pidie. Gampoeng janda
inilah yang kemudian menjadi lokasi dari
figur utama kronotop dokumenter saya.
Dokumenter Testimoni Partikular Sebagai
Kontra Politik: Proses Perekaman
Menurut kronotop nasionalisme militeristik
yang bersikulasi secara dominan di ruang
publik (berita koran, TV, dan bentuk
pertunjukkan publik lainnya), Aceh adalah
ruang untuk berperang dan menindak para
perusuh negara. Sebagai akibatnya, korban
yang mendiami ruang yang sama (Aceh) juga
dijadikan liyan yang atau kesezamanannya
(coevality) telah disangkal (Fabian, 1983).
Hal ini saya temui, misalnya ketika seorang
kawan merasa aneh dengan niat saya untuk
bersusah payah shooting dokumenter di
daerah konflik seperti Aceh. Katanya,
“Mengapa kamu ingin pergi ke Aceh?
Biarkan saja Aceh merdeka. Daerah kecil
yang sok!” (Danusiri, 2004).
Oleh karena itu, dalam kerangka kerja
saya, merekam kesaksian korban adalah
sebuah chronopolitics karena saya hadir di
waktu-ruang yang sama dengan para korban
DOM Aceh sehingga bisa menghasilkan
representasi tandingan terhadap kronotop
militeristik. Kronotop yang saya konstruksi
melalui proses perekaman saya sebut
145
kronotop testimoni partikular—kronotop
kontra-politik yang memaknai pengungkapan
lokalitas dan partikularitas dari kesaksian
korban sebagai hal penting dan mendesak
dalam konteks Indonesia pasca-Suharto
dengan tidak menciptakan jarak dengan
korban, namun justru mengonstruksi
pemahaman yang intim.
Perekaman (shooting) di Aceh hanya
dilakukan oleh saya dan kamerawan, yaitu
Rachmat Syaiful. Kami membawa kamera
Mini-DV VX1000, tipe kamera yang pada
saat itu sangat populer di kalangan pembuat
dokumenter sebagai kamera dengan kualitas
gambar terbaik namun ringan karena
bentuknya
berupa
kamera
genggam
(handycam). Situasi di lapangan memang
tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya.
Dua aktivis LSM yang berbasis di Banda
Aceh, Evi Zain (waktu itu tergabung di Forum
LSM Aceh) dan Yusrizal (Koalisi NGO
HAM), bergabung dalam tim dokumenter.
Kami bergerak ke Pidie, tapi ternyata kami
tidak bisa mengakses Kampung Cot Keng
yang menjadi target. TNI berseliweran di
mana-mana dan “kontak” (perang senjata
terbuka) sedang merebak di berbagai daerah
di Pidie yang memang ditengarai sebagai
basis utama GAM.
Setelah melalui perjalanan hampir tiga
jam dengan minibus dari Banda Aceh, kami
berhenti di pusat Kecamatan Mutiara di Pidie.
Pada saat itu saya dan tim hanya bisa
mengakses sejauh titik itu. Kekecewaan
meliputi wajah-wajah kami karena tidak bisa
mendatangi kampung yang telah kami
rencanakan. Waktu yang kami miliki saat itu
kurang dari 15 hari untuk perekaman. Solusi
yang ditawarkan oleh Evi adalah beralih ke
Kampung Tiro di Kecamatan Tiro/Truseb
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
sebagai lokasi perekaman. Kampung ini
terkenal karena namanya yang diasosiasikan
dengan Tengku Hasan di Tiro (1925-2010),
salah satu pendiri GAM. Daerah ini juga
masuk ke dalam periode DOM pertama atau
Operasi
Jaring
Merah
(1989-1998).
Pelanggaran HAM oleh militer Indonesia
banyak terjadi di daerah ini karena seringnya
perang bersenjata terjadi. Setelah DOM
berakhir, justru daerah Tiro dianggap “aman”
karena kontak senjata lebih banyak terjadi di
daerah lain di seputar Kabupaten Pidie. Kami
akhirnya setuju untuk menjadikan daerah ini
lokasi
baru
perekaman
dokumenter.
Harapannya, kami bisa menemukan aktoraktor yang bersedia berbagi kesaksian dan
pengalaman luka mereka sebagai korban
konflik.
Kami menginap di puskesmas
Kecamatan Tiro/Truseb yang dikepalai oleh
Dokter Taufik yang berasal dari Medan. Kami
disarankan untuk tidak melakukan aktivitas
perekaman secara terbuka, terutama untuk
menghindari pantauan militer yang berkantor
di markas koramil (komando rayon militer),
tak jauh dari puskemas. Kami menyewa mobil
bak terbuka dan pergi menuju ke arah
Pegunungan Bukit Barisan untuk menemui
para korban di permukiman Blang Keudah
yang berjarak sekitar 30 menit dari
puskesmas. Dari informasi yang didapatkan
Evi dan Yusrizal, daerah Blang Keudah inilah
salah satu daerah yang memiliki tingkat
keparahan tinggi dalam menghadapi teror
tentara Indonesia di masa DOM I. Daerah
pegunungan adalah daerah strategis untuk
GAM bersembunyi dan bermarkas, sehingga
masyarakat yang hidup di sekitar pegunungan
kerap menjadi target operasi TNI karena
dicurigai membantu atau menjadi anggota
GAM.
Tidak banyak penduduk yang masih
tinggal di perkampungan karena sebagian
besar sudah mengungsi ke Masjid Abu Daud
Beureuh di kota Kecamatan Mutiara.
Beberapa orang dan keluarga masih tinggal di
kampung untuk beberapa hari karena
mengerjakan sawah mereka (Blang Keudah
memiliki areal pertanian yang subur). Tidak
mudah mencari para korban yang bersedia
bersaksi di depan kamera. Mereka yang
bersedia terdiri atas para korban yang dekat
dengan mantan pemimpin desa dan memiliki
informasi yang baik mengenai situasi
keamanan terkini. Sesuai dengan desain video
dokumenter, prioritas kami adalah untuk
merekam kesaksian luka perempuan, baik
yang secara langsung atau tidak langsung,
mengalami kekerasan oleh militer Indonesia.
Saya bersikeras untuk tinggal di kampung
agar bisa merekam tidak saja kesaksian
korban, namun juga kehidupan terkini
keseharian mereka. Atas saran orang
kampung, hal itu tidak dimungkinkan karena
akan
membahayakan
keamanan
tim
dokumenter maupun orang-orang yang masih
tinggal di kampung. Akhirnya kami hanya
bisa ulang-alik antara puskesmas tempat kami
menginap dan area permukiman Blang
Keudah untuk menemui para aktor.
Ketegangan terjadi antara saya dengan
kamerawan, Rachmat Syaiful, tentang
bagaimana merekam kesaksian para korban.
Syaiful memilih untuk fokus pada aspek lisan
yang dituturkan oleh para korban mengenai
kesaksian, luka, dan ingatan akan kekerasan
yang mereka alami, sedangkan saya tertarik
pada hubungan antara aspek kelisanan dan
kehidupan sehari-hari mereka. Setelah
146
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
berdiskusi, akhirnya kami menyepakati untuk
menentukan
terlebih
dahulu
praktik
keseharian yang hendak direkam sesuai
dengan jadwal yang direncanakan dan bukan
praktik keseharian yang direkam oleh kamera
tanpa antisipasi. Akan tetapi, upaya
melakukan penjadwalan secara terperinci
tidaklah memungkinkan dalam situasi
perekaman yang penuh kewaspadaan. Bahkan
pada suatu titik kami harus memperpendek
rentang waktu perekaman dan segera
meninggalkan kampung demi alasan
keamanan.
Para aktor yang kami rekam
kesaksiannya dibagi atas korban pelanggaran
berat dan korban pelanggaran sosial ekonomi.
Selain itu, kami juga merekam penjelasan dari
beberapa aktor mengenai kehidupan di Tiro
selama masa operasi militer. Kami
diperkenalkan oleh Ridwan, mantan staf desa
dan teman Dokter Taufik, kepada para aktor
sebagai mahasiswa dan orang LSM—dua
identitas yang pada saat itu dikonotasikan
sebagai aktor perubahan Aceh.5 Tiap aktor
dipersilakan memilih sendiri lokasi untuk
mereka menyampaikan kesaksian dan
menunjukkan luka sebagai korban. Aisyah—
suami dan dua anaknya dibunuh oleh tentara
karena dituduh sebagai anggota GAM—
memilih untuk bersaksi di depan rumahnya
saja. Adapun Usman dengan penuh semangat
mengajak kami untuk mendatangi sebuah
“rumah Aceh” yang terletak di pinggir
permukiman. Rumah kayu khas Aceh ini
adalah tempat yang dijadikan markas Batalion
Infrantri 126 selama operasi. Mardiyah yang
mendengar ini juga ikut ke lokasi, bahkan
kemudian mengarahkan kami untuk pergi ke
5
Pintu Satu, yaitu lokasi markas Kopassus
(Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan
Darat) yang dijadikan tempat interogasi dan
penyiksaan para korban. Di lokasi inilah
Mardiyah memperagakan bagaimana dia
dituduh telah membantu GAM dengan
menyediakan beras dan diinterogasi dengan
penyiksaan.
Kelompok pemuda yang dipimpin
Faisal dan Ismet memperagakan bagaimana
mereka dipaksa untuk jaga malam dan dilatih
militer untuk membantu tentara beroperasi.
Dalam keseluruhan perekaman ini, ingatan
atas pembunuhan, penyiksaan, dan kekerasan
yang dialami oleh para aktor dipertunjukkan
tidak saja dalam ekspresi ketubuhan, tetapi
juga melalui pertunjukkan “geografi teror” di
daerah Tiro. Lewat mobilitas dari lokasi ke
lokasi yang diarahkan oleh para aktor, tim
dokumenter bisa merasakan dan menyaksikan
bahwa teror yang dibangun oleh militer
Indonesia saat DOM dilakukan dengan
mengubah Tiro menjadi lanskap pengecualian
(landscape of exception) yang mengubah
kehidupan warga kampung sebagai warga
negara menjadi hidup yang hampa (bare life)
sehingga mereka diingkari hak-haknya dan
bisa dibunuh (Agamben, 1998).
Kronotop sebagai “ekspresi spasiotemporal” (temporal-spatio expression)
adalah leitmotif yang dapat menjadikan segala
sesuatu menjadi bermakna, sebagaimana
ditegaskan oleh Bakhtin (1981: 258),
“Consequently, every entry into the sphere of
meanings is accomplished only through the
gates of the chronotope.” Bagaimana orang
Tiro memahami perubahan kampung mereka
menjadi geografi teror? Ada dua folklor yang
SIRA (Sentra Informasi Refrendum Aceh) adalah satu lembaga sipil yang punya peran besar dalam perubahan
politik di Aceh yang terdiri dari mahasiwa, aktivis dan santri.
147
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
disampaikan kepada saya: Hikayat Perang
Sabil (dalam versi lokal Tiro) dan pepatah
kameng gampoeng. Dalam hikayat perang
jelas disebutkan bahwa periode penerapan
DOM di Aceh adalah “masa yahudi duk
rumoh geudong” (masa gelap di rumah
geudong). Rumah geudong menjadi penanda
dari geografi teror yang berlangsung di
kampung Tiro. Masyarakat selalu bertanya
kenapa mereka yang selalu dijadikan sasaran
penyiksaan? Pepatah “kameng glee nyang
pajoh jagung, kameng gampoeng nyang
keunong geulawa, ” (kambing gunung yang
makan/curi jagung, kambing kampung yang
kena pukul) menjadi metafora yang mereka
gunakan untuk menjelaskan pengalaman
buruk mereka.
Mobilitas kami menjelajahi kampung
untuk menemui para aktor kemudian tersendat
ketika kami menemukan bahwa rumah
penyiksaan di Pulo Kenari sudah runtuh.
Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa
rumah itu tiba-tiba berubah menjadi puingpuing rata dengan tanah. Dua hari kemudian
datang pesan kepada kami bahwa Komandan
Koramil ingin bertemu dengan saya. Syaiful
segera menyembunyikan kaset-kaset hasil
perekaman dan Ismet yang juga tinggal di
puskesmas selama proses perekaman
menyembunyikan kertas teks Hikayat Perang
Sabil di balik pelapis dinding. Saat saya
berkunjung ke kantor koramil, saya jelaskan
bahwa kami sedang melakukan penelitian
mengenai kondisi ekonomi masyarakat pascaDOM. Untuk memperkuat penjelasan
tersebut, saya pun menunjukkan surat
pengantar dari ELSAM yang menyatakan hal
ini.6
Kami berunding setelahnya dan
memutuskan untuk segera kembali ke Banda
Aceh dalam dua hari ke depan. Suasana
politik memang mulai genting karena tuntutan
agar dilaksanakan referendum di Aceh
semakin masif dikampanyekan oleh SIRA dan
mahasiswa di Aceh.7 Adegan terakhir yang
kami rekam adalah adegan Faisal, Ismet, dan
tim pemuda memperagakan pelatihan ala
militer yang dipaksakan oleh TNI kepada
mereka. Selain itu, kami juga merekam
Teungku
Iskandar
mempertunjukkan
pembacaan Hikayat Perang Sabil di sebuah
dataran yang agak tinggi menjauh dari
perkampungan. Teungku Iskandar sengaja
memilih tempat yang sepi tersembunyi karena
hikayat tersebut telah menjadi simbol
perlawanan politik yang populer. Kami
meninggalkan Tiro dua hari lebih cepat dari
yang kami rencanakan.
Korban sebagai Montase: Proses Editing
Proses editing dengan teknologi digital belum
sepenuhnya tersedia pada saat itu di Jakarta.
Dono, sang editor, harus mengalihkan
rekaman dari kaset Mini-DV ke kaset
Betacam karena alat untuk memutar kaset
Mini-DV belum tersedia. Proses dimulai
dengan membuat catatan tentang seluruh
adegan yang telah direkam. Saya sebagai
sutradara, kemudian bekerja membuat
skenario baru untuk menyusun kisah dalam
bentuk video dokumenter pendek.
6
Surat izin ini sudah saya persiapkan sebelumnya dan tidak menyebutkan soal pelanggaran HAM.
Akhirnya pada tanggal 8 November 1999, SIRA berhasil membuat demonstrasi besar menuntut referendum Aceh.
Skala demonstrasi ini berhasil memaksa elit politik dan agama di Aceh untuk ikut mendukung pilihan referendum
(lihat Reid, 2004)
7
148
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
Sebagaimana
tergambar
pada
judulnya, video dokumenter ini menggunakan
folklor sebagai leifmotif ekspresi spasiotemporal dalam menstrukturkan aspek naratif
film—suatu strategi yang terinspirasi dari film
dokumenter Moving the Mountain (sutradara
Michael Apted, 1994) tentang protes tahun
1989 di Tiananmen Square, Beijing. Film
dibuka dengan memperlihatkan situasi
kampung pasca-Jenderal Wiranto mencabut
DOM namun mengirimkan tentara PPRM
untuk menebar teror baru. Hasilnya adalah
padi yang rusak terbengkalai dan penduduk
kampung pergi mengungsi ke kota. Lewat
adegan di pengungsian Masjid Abu Daud
Beureuh,
Pidie,
ditampilkan
situasi
pengungsian yang tidak layak.
Sekuen Satu: strukturnya adalah
interfase
antara
Teungku
Iskandar
membacakan Hikayat Perang Sabil di atas
bukit dengan para aktor mempertunjukkan
kesaksian
dan
luka
mereka
yang
dikategorikan sebagai pelanggaran HAM
berat. Pada babak ini tampil Aisyah (suami
dan dua anak lelakinya dibunuh di depan
matanya sendiri), Kartini (anak lakinya
diciduk oleh tentara), Mardiyah dan Usman
(keduanya dicurigai membantu GPK/Gerakan
Pengacau Keamaan—istilah pemerintah
Indonesia untuk GAM—dan mengalami
interogasi dan penyiksaan fisik).
Sekuen Kedua: dibuka dengan adegan
anak perempuan Aisyah yang menjelaskan
apa yang terjadi pada ibunya setelah peristiwa
penembakan terjadi. “Orang kampung diam
saja. Mereka menjaga jarak dengan kami.
Mereka mau dihubungkan dengan kami atau
GPK,” Fatimah, sang anak, menjelaskan
dalam bahasa Aceh. Fokus dari bagian ini
adalah menjelaskan kepada para penonton
149
bahwa situasi daerah Tiro yang dikuasai oleh
tentara membuat penduduk susah bekerja dan
bergerak di luar rumah, terutama bagi mereka
yang sawahnya dekat dengan pegunungan.
Hal ini menggambarkan pelanggaran hak
sosial-ekonomi dari diberlakukannya operasi
militer. Pada bagian inilah ditampilkan
adegan-adegan kesaksian dari para pemuda
Tiro yang dipaksa ikut latihan militer dan
berjaga keamanan di kampung. Lewat
penjelasan Dokter Taufik, penonton menjadi
tahu bahwa sejak tertembaknya Danramil
(Komandan Rayon Militer) dan seorang
dokter puskesmas di tahun 1989, tidak ada
lagi dokter yang ditempatkan di Puskesmas
Tiro. Bila pada sekuen pertama moda
representasinya adalah gabungan antara moda
puitik dan moda pertunjukkan (performance),
maka pada sekuen kedua moda yang utama
adalah ekspositoris (penjelasan).
Masalah
kemudian
muncul:
bagaimana menutup dokumenter ini?
Di lapangan, Evi pada suatu waktu
bercanda dengan Azimah, putri remaja
Aisyah. Oleh karena mereka bercanda dalam
bahasa Aceh, saya tanyakan apa yang mereka
tertawakan. Setelah mendengar penjelasan
mereka, saya pun memutuskan untuk
merekam ulang percakapan satire itu dengan
kamera. Adegan yang tervisualisasi ialah:
Evi bertanya, “Kapan akan menikah?”
Dijawab oleh Azimah, “Setelah merdeka, bila
ada yang mau.” Evi kembali bertanya,
“Kenapa
setelah
merdeka?”
Dengan
cekikikan, Azimah menjawab, “Lebih baik
menikah setelah itu. Untuk apa menikah kalau
terus khawatir? Bagaimana kalau tentara
mengambil suami saya dan dia disiksa? Saya
akan jadi janda. Saya jadi sedih. Jadi, lebih
baik merdeka dulu.”
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
Setelah melihat antusiasme anak-anak
Aisyah dalam menjawab pertanyaan semacam
ini, Evi dan saya menanyakan pertanyaan
serupa ke aktor-aktor lain. Namun,
percakapan pendek Evi dengan Azimah tetap
menjadi adegan yang menarik bagi saya tanpa
terlalu paham sepenuhnya ketika itu kenapa
saya sedemikian tertarik dengan adegan
tersebut.
Ketertarikan saya terhadap adegan
satire itu bisa dipahami dalam beberapa
perspektif. Pertama, berkenaan dengan cara
korban sebagai subjek diproduksi oleh
kronotop nasionalisme otoritarian. Dalam
studinya terhadap pelaporan Majalah Tempo
tahun 2001 mengenai konflik Aceh, Siegel
(2002) fokus pada pandangan kelas menengah
yang tidak peduli terhadap konflik tersebut
dan setuju pada penanganan militeristik
dengan mengirimkan pasukan lebih banyak ke
Aceh (ini tercermin dari polling pendapat
pembaca Tempo). Salah satu karakter dari
nasionalisme Orde Baru ialah mengubah
pandangan
terhadap
“kelas
bawah”
(underclass) dari “rakyat”—yang berarti
“kekuatan politik aktif” (an active political
force) yang khas Orde Lama—menjadi
“massa”—yang berarti kerumunan—sebagai
konsekuensi dari ideologi persatuan bangsa.
Siegel (2002) menunjukkan bahwa ketika
Tempo melaporkan berita mengenai konflik,
rakyat Aceh digambarkan hanya sebagai
korban-korban pasif (“Acehnese are passive
victims”) yang apolitis tanpa aliansi politik
yang jelas. Bahkan tidak dijelaskan oleh
Tempo bahwa korban yang kebanyakan petani
menjadi simpati kepada GAM justru karena
teror TNI; dan tidak dijelaskan pula bahwa
para mahasiswa sesungguhnya tidak setuju
dengan politik GAM yang berkarakter etnonasionalisme (Siegel, 2002).
Kronotop testimoni partikular dalam
dokumenter Kameng Gampoeng adalah
kronotop tandingan yang mengedepankan
korban bukan sebagai subjek yang pasif.
Satire Azimah mengungkapkan hal itu.
Azimah bukanlah korban sebagaimana yang
dilaporkan oleh Tempo: pasif, anonim, dan
tidak perlu dijelaskan posisi politiknya karena
bagian dari “massa” yang apolitis belaka.
Justru sebaliknya, Azimah adalah bagian dari
rakyat yang bisa memiliki pemikiran politik,
sehingga dia menjadi bagian dari kekuatan
politik baru. Humor satire sebagai strategi
politik memiliki kekuatan dalam hal “…
mengombinasi kepolosan dan keseriusan
sebagai cara yang bisa mengubah hubunganhubungan dan melampaui rasionalitas”
(Sorensen, 2008). Azimah paham bahwa
menurut rasionalitas negara, TNI akan bisa
menjaga keamanan nasional dengan baik dan
keamanan akan segera tercipta. Dengan satire,
Azimah melakukan kontra-logika dengan
meng-irasionalitas-kan retorika negara yang
me-rasionalitas-kan keamanan Aceh sebagai
strategi yang penting bagi stabilitas teritorial
tentara dalam memelihara eksistensi mereka.
Sebagai tanggapan atas homogenisasi
dan
netralisasi
korban
sebagai
massa/kerumunan, maka pada bagian akhir
video saya mengonstruksi sebuah montase
(montage) yang mengindividualisasi setiap
aktor dalam mengungkapkan pemaknaan
mereka
terhadap
hubungan
antara
pengalaman kekerasan yang mereka alami
dengan situasi politik Aceh kontemporer.
Dengan demikian, sekuen terakhir dibuka
dengan Hikayat Doda Idi yang dinyanyikan
oleh seorang nenek di pengungsian di
150
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
Beureun—lagu pengantar tidur anak yang
diliputi oleh kisah kepahlawanan perang
melawan kaphe (penjajah) dan digunakan
dalam naratif film karena popularitasnya pada
saat itu sebagai media ungkap keluhan orang
Aceh terhadap kekerasan militer (Al Chaidar,
1998). Hal ini memperjelas struktur naratif
atas waktu dalam dokumenter: hikayat masa
lalu mengarakterisasi geografi teror di dalam
dua sekuen awal (sekuen ke-1 & 2),
sedangkan hikayat masa kini yang dipenuhi
imajinasi kemerdekaan adalah gambaran
sekuen penutup (sekuen ke-3).
Sekuen penutup menjukstaposisi
kumpulan wawancara dengan tujuh aktor dan
potongan-potongan
imaji
yang
menggambarkan situasi teror militer serta
ekspresi merdeka dan referendum. Kumpulan
terakhir ini terdiri atas footage berita TV
mengenai pelanggaran HAM Simpang KKA,
Kampung Kandang, dan Beutong, dan juga
grafiti jalanan tentang referendum, ditambah
satu imaji pengibaran bendera GAM (yang di
lapangan kami rekam karena keinginan Ismet
dan kawan-kawan untuk menyertakan imaji
tersebut di dalam video dokumenter). Lima
aktor di awal sekuen memberikan pernyataan
bahwa mereka ingin merdeka atau referendum
diselenggarakan agar bisa lewat dari teror.
Pernyataan Kartini dan satire Azimah
menutup sekuen tersebut. Kartini, dalam
adegan, hanya diam ketika ditanya, “Ibu mau
apa?” Setelah diam sejenak, Kartini
menjawab, “saya tidak tahu mau jawab apa.”
Sejenak kemudian pengarahan datang dari
anak lelakinya agar Kartini menjawab dengan
aspirasi ingin berpisah dengan Indonesia dan
Jawa.
Jukstaposisi ini hendak memberikan
persepsi bahwa ada “hubungan yang
151
transparan” antara aspirasi kemerdekaan
dengan pengalaman luka dari para aktor.
Montase adalah metodologi editing yang
tujuannya “mengidealisasikan ruang-waktu”
(idealization of space and time) (Umberto
Barbaro dikutip Chanan, 2000) karena waktu
dan ruang mengalami pengorganisasian baru
lewat teknik editing, terlepas dari realitas
waktu-ruang
saat
perekaman,
demi
mengungkap sebuah makna yang ideal.
Montase selalu identik dengan dokumenter
ekspositoris karena memiliki tujuan “… to
impose its terpretation of an event on the
spectator” (Bazin, 2005: 26). Dengan
demikian, transparansi hubungan antara
pernyataan para aktor dengan ikon-ikon
kemerdekaan dan referendum adalah hasil
konstruksi saya sebagai pembuat film.
Kebisuan Kartini saat ditanya soal
masa depan dan satire Azimah menunjukkan
bahwa korban dan pengalaman teror bukanlah
fenomena yang sederhana dan mudah
dideteksi. Video dokumenter ini telah
mengonstruksi visibilitas para aktor sebagai
korban DOM dengan testimoni dan
pemeragaan pengalaman teror dan kekerasan
yang mereka alami. Dari visibilitas ini
diharapkan penonton/publik bisa memahami
dimensi dari para aktor sebagai korban politik.
Namun, apakah para aktor tersebut hidup
hanya sebagai korban? Dimensi kemanusiaan
dari para aktor hanya mendiami dan tinggal di
ranah invisibilitas dari video dokumenter—
tersembunyi dari saya sebagai sineas dan
penonton. Kronotop nasionalisme telah
menjadikan
korban
sekadar
“massa/kerumunan”, sehingga mereka tidak
terdengar suaranya di Jakarta (Siegel, 2002).
Kendati demikian, tak dimungkiri
bahwa visibilitas korban dalam dokumenter
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
ini turut melanggengkan reproduksi dari
oposisi biner “penindas–korban” (oppressor–
victim) dan gagal untuk memahami
multidimensionalitas subjek politik yang
disebut korban itu. Bagaimana faktor kelas,
gender, dan etnisitas berperan dalam proses
rekonstruksi subjektivitas korban? Bukankah
korban itu tidak hanya orang Aceh saja,
namun juga petani Jawa yang hidup di Aceh
yang juga menjadi korban kekerasan GAM?8
Dualisme TNI–korban Aceh juga telah
mengukuhkan eksistensi GAM sebagai
“single bad guys”, menafikan keragaman dan
pertentangan dalam tubuh GAM, dan pada
gilirannya mereduksi porsi tanggung jawab
(liability) negara dalam penyelesaian kasus
HAM masa lalu (Drexler, 2006).
Lantas, model partikularitas macam
apa yang saya praktikkan dalam dokumenter
ini? Montase pada prinsipnya adalah
mengombinasi unit-unit ke dalam suatu
komposisi waktu dan ruang yang baru demi
produksi makna yang baru. Bila kita ikuti
pandangan MacDougall (1998) bahwa gaya
sinema adalah teori pengetahuan, maka
montase adalah model pengetahuan yang
memahami yang-partikular sebagai unit yang
berkarakter atau berdimensi tunggal, sehingga
bisa dengan mudah dijukstaposisi dengan unit
partikular lain untuk bisa memberikan
gambaran
mengenai
totalitasnya.
Partikularitas dalam model konstruksi partwhole ini melihat unit sebagai manifestasi dari
totalitas keutuhan (whole). Individu dalam
model ini memiliki kronotop yang abstrak
karena muncul sebagai subjek yang mewakili
generalisasi ketimbang mengartikulasikan
keberagamannya.
8
Sebaliknya, kronotop partikularitas
dalam etnografi, saya berargumen, adalah
memahami subjek dalam kontinuitas, seperti
yang diajukan oleh Abu-Lughod (1991)
dengan kategori “etnografi dari yangpartikular” (ethnographies of the particular).
Partikularitas semacam ini tidak melihat
subjektivikasi sebagai proses yang transparan,
melainkan melihat individu dalam ruang dan
waktu konkret senantiasa bergulat dengan
proses menjadi subjek yang secara objektif
dipaksakan oleh institusi-institusi sosial
politik. Dengan demikian, antara individu
(aktor sosial) dengan subjek (sosial atau
politik) tidak terdapat hubungan langsung dan
transparan, melainkan senantiasa dalam
proses negosiasi yang kompleks dalam ruang
waktu yang konkret. Saya sebut sebagai
kontinuitas karena para aktor hidup dalam
multidimensi
individualitasnya
yang
berkesinambungan sebagai spektrum.
Epilog
Dari dua kontras pemahaman mengenai
mengenai partikularitas di atas, saya
menunjukkan bahwa video dokumenter
Kameng Gampoeng hanya fokus pada
penunggalan dimensi para aktor ke dalam satu
tipe, yaitu korban DOM Aceh. Satire Azimah
dan kebisuan Kartini telah membangkitkan
rasa ingin tahu saya untuk memahami
pengalaman mereka dan para aktor lainnya
melampaui identitas mereka sebagai korban.
Dengan memahami spektrum individualitas
mereka dan bagaimana mereka bergulat
dengan perubahan hubungan-hubungan sosial
berkenaan dengan posisi subjektif mereka
https://www.liputan6.com/news/read/57093/warga-desa-kem-gam-membantai-transmigran
152
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
sebagai korban dan aktor sosial, kita bisa
memahami bahwa bagi seseorang, menjadi
korban kekerasan HAM bukan hanya disrupsi
dalam keseharian, tetapi juga bagian dari
keseharian yang terus berlanjut (Das, 2008:
195). Sinema, sebagai medium sensori,
seharusnya bisa mengungkap visibilitas
spektrum
tersebut
dan
bukan
menyembunyikannya.
Ucapan Terima Kasih
Tulisan ini saya dedikasikan kepada
almarhum Professor Mary Steedly (December
16, 1946 - January 4, 2018) yang senantiasa
membimbing dan menginspirasi saya hingga
akhir hayatnya. Terima kasih kepada
Professor Byron Good yang telah
memberikan waktu kepada saya untuk bisa
menuliskan karya ini.
Saya juga ucapkan terima kasih
kepada dua reviewer anonim. Terakhir, saya
ucapkan terima kasih sebagai tim yang
memungkinkan film dokumenter dalam
tulisan ini bisa terwujud. Mereka adalah
Ifdhal
Kasim,
Sandra
Moniaga,
Ichwandiardono, Rachmat Syaiful, Thoersi
Argeswara, Dwi Koendoro BR, Cik Dewasih,
Dini Aulia, Sugiyanto, Evi Zain, Yusrizal,
Ayi Sarjevo dan Renati Adriani.
Referensi
Abu-Lughod, Lila.
1991
“Writing against Culture,” in Richard G. Fox (ed.), Recapturing Anthropology:
Working in the Present. Santa Fe, N.M.: School of American Research Press, Pp. 137–
62.
Agamben, G.
1998
Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford University Press.
Agha, A.
2007
"Recombinant Selves in Mass Mediated Spacetime." Language & Communication
27(3): 320-335.
Alatas, I. F.
2016
"The Poetics of Pilgrimage: Assembling Contemporary Indonesian Pilgrimage to
Ḥaḍramawt, Yemen." Comparative Studies in Society and History, 58(03): 607–635.
https://doi.org/10.1017/S0010417516000293
Al-Chaidar, Ahmad, S. M., & Dinamika, Y.
1999
Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer
(DOM) di Aceh, 1989-1998. Pustaka Al-Kautsar.
153
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
Anderson, B.
2006
Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso.
Bakhtin, M. M., Wright, J., & Holquist, M.
1981
The dialogic imagination: Four essays. University of Texas Press.
Bazin, A.
2005
What Is Cinema? (1976th ed.). University of California Press.
Bronkhorst, D.
2002
Menguak Masa Lalu Merenda Masa Depan: Komisi Kebenaran di berbagai Negara.
ELSAM Jakarta.
Bruzzi, S.
2006
New Documentary. Routledge.
Carey, J. W.
1992
Communication as Culture: Essays on Media and Society. Psychology Press.
Das, V.
2008
"Violence, Gender, and Subjectivity." Annual Review of Anthropology 37(1): 283–
299. https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.36.081406.094430
Derrida, J.
1972
"Signature Event Context," in A. Bas (trans.), Margins of Philosophy (1982nd ed.).
Chicago: Univ. of Chicago Press, Pp. 307–330.
Drexler, E.
2006
"History and Liability in Aceh, Indonesia: Single Bad Guys and Convergent
Narratives." American Ethnologist 33(3): 313–326.
https://doi.org/10.1525/ae.2006.33.3.313
Good, M.-J. D., Hyde, S. T., Pinto, S., & Good, B. J.
2008
Postcolonial Disorders. University of California Press.
Hanan, D.
2012
"Observational Documentary Comes to Indonesia," in T. Baumgartel (ed.), Southeast
Asian Independent Cinema, Pp. 105–116.
https://doi.org/10.5790/hongkong/9789888083602.003.0009
154
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
Kasim, I. (ed.).
2003
Kebenaran vs. keadilan: Pertanggungjawaban pelanggaran HAM di masa lalu.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
Larkin, B.
2008
Signal and Noise: Media, Infrastructure, and Urban Culture in Nigeria. Duke
University Press.
MacDougall, D.
1998
Transcultural Cinema. Retrieved from
https://books.google.co.id/books?id=hoxUQaz3cuEC&printsec=frontcover&dq=Mac
Dougall+Ethnographic&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjVkMeD8srhAhVNFHIKHUhJ
CTQQ6AEIKjAA#v=onepage&q=MacDougall%20Ethnographic&f=false
2001 "Renewing Ethnographic Film: Is Digital Video Changing the Genre?" Anthropology
Today 17(3): 15–21. https://doi.org/10.1111/1467-8322.00060
Mitchell, W. J. T.
2005
What Do Pictures Want?: The Lives and Loves of Images. University of Chicago
Press.
Reid, A.
2004
Spyer, P.
2002
"War, Peace and the Burden of History in Aceh." Asian Ethnicity 5(3): 301–314.
https://doi.org/10.1080/1463136042000259761
"Fire without Smoke and Other Phantoms of Ambon’s Violence: Media Effects,
Agency, and the Work of Imagination." Indonesia 74: 21.
https://doi.org/10.2307/3351523
Stasch, R.
2011
"Textual Iconicity and the Primitivist Cosmos: Chronotopes of Desire in Travel
Writing about Korowai of West Papua: Chronotopes of Desire in Travel Writing about
Korowai of West Papua." Journal of Linguistic Anthropology 21(1): 1–21.
https://doi.org/10.1111/j.1548-1395.2011.01080.x
Steedly, M.
1999
"The State of Culture Theory in the Anthropology of Southeast Asia." Annual Review
of Anthropology 28(1): 431–454. https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.28.1.431
155
�ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 39 NO 2 2018
2013
"Transparancy and Apparition: Media Ghosts of Post-New Order Indonesia," in
School of Advanced Research Advanced Seminar Series. Images That Move, Pp. 257–
294. Santa Fe: SAR Press.
156
�
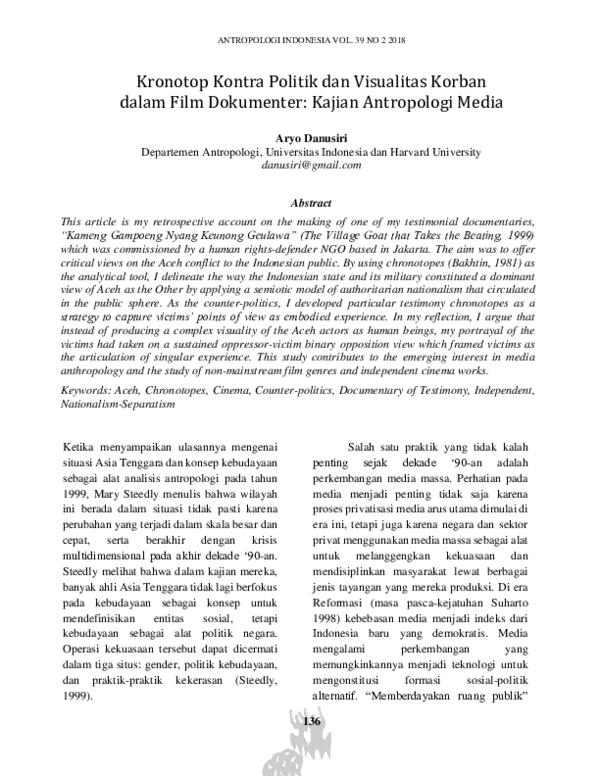
 Aryo Danusiri
Aryo Danusiri