Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
Catatan Singkat Mengenai Rencana Pembentukan Undang-Undang yang Mengatur MPR secara Terpisah dengan Lembaga Legislatif Lainnya
Catatan Singkat Mengenai Rencana Pembentukan Undang-Undang yang Mengatur MPR secara Terpisah dengan Lembaga Legislatif Lainnya
Related Papers
The shift from a parliament supremation to constitution supremation after the reformation brought a basic change in the state structur of Indonesia. MPR is not the highest institution of this country but has become a higher institution and has an equal position as other higher institutions. It has become the main reason of not putting MPR/S’ law’s products up as in the law hierarchy in Indonesia based on Law Number 10/2004. However, Law Number 12/2011 put MPR’s decision in the hierarchy has made a new problematique. First of all, as seen on its position is above the laws and below the constitution. Second, the validity of MPR’s decision in the Law Number 12/2011. Third, related to which institution that has authority to examine MPR’s decision when it contradicts to Indonesian constitution.Key Word : TAP MPR, Position, Law Status, Authority of Examination
Jurnal Hukum Positum
Prospek Kewenangan MPR dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR yang Bersifat MengaturJurnal Hukum & Pembangunan
Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan DI IndonesiaJurnal Abdimas Mandiri
Studi Keberadaan Tap MPR Ri Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20112019 •
ABSTRAKStudi ini menjelaskan posisi dan kedudukan Ketetapan MPR RI dalam hirarki perundangan di Indonesia yang dilakukan dengan teknik literatur review dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia merupakan produk hukum formil dari lembaga tertinggi negara pra amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi konsekuensi perubahan status Majelis Pemusyarawatan Rakyat Republik Indonesia dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Konsekuensi dari amandem tersebut adalah TAP MPR RI tidak lagi menjadi rujukan pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Perundang-Undangan. Namun setelah direvisi dan ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan im...
MPR Decree was in hierarchical manner betweenl945 and theAct which in theory in the group of legal norms Staats grund gesetz (Rules of the State/State Basic Rules). MPR Decree under the 1945 Constitutionis a consequence of the position of the MPR as executor of full sovereignty of the people and the country's top institutions. However, 1945 Constitution amendment no longer determine the MPR as executor of full sovereignty of the people. Moreover, MPR are no longer the highest state institution. Therefore, it has implications for the existence of the Legislative Actin the hierarchy of legislation. MPRS Decree No. XXA4PRS/1966 and MPR Decree No.IIL&IPR/2000 put MPR Decree in the second place after 1945 Constitution. LawNo. l0 of 2004 does not recognize the MPR decree as one type of legislation. Law No.12 of 20 i 1 put back MPR decree as one type of legislation. This paper attempts to discuss the rationale of the dynamic development of MPR Decree position in the hierarchy of legislation before the Amendment of 1945 Constitution to the promulga-tion of Law No. l2 of 20 I I , after the Amendment of I 945 Constitution. Ketetapan MPR adalah salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan khas Indone-sia. Secara hirarkis berada di antara UUD 1945 dan Undang-Undang yang secara teoretik masuk dalam kelompok norma hukum Staatsgrundgesetz (Aturat Dasar Negara/Aturan Pokok Negara). Keberadaan Ketetepan MPR sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang berada.di bawah UUD 1945 merupakan konsekuensi dari kedudukan MPR sebagai pelaksana penuh kedaulatan rakyat dan sebagai lembaga negara tertinggi di antara lembaga-lembaga negara laimya, sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Namun Perubahan ULID 1 945 yang menentukan tidak lagi menempatkan MPR sebagai pelaksana penuh kedaulatan rakyat dan bukan pula sebagai lembaga tertinggi negara telah berimplikasi pada keberadaan Ketetapan MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Jika Ketetapan MPRS No. XX/\4PRS/l966 dan Ketetapan MPR No. IIIA4PR/2000 keberadaan Ketetapan MPR masih tetap ditempatkan dalam urutan kedua (setelah UUD 1945) dalam hirarki peraturan perundang-undangan, maka setelah Perubahan Ketiga UUD 1945 Ketetapan MPR tidak lagi diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangandalam UU No. l0 Tahun 2004. Namun dalam UU No. l2Tahun2011 keberadaan Ketetapan MPR kembali diakui sebagai salah satu jenisperaturanperundang-undangansebagaimanasebelumlahirnyaUUNo.l0Tahun2004.Tulisan ini mencoba membahas dasar pemikiran daridinamika perkembangan kedudukan Ketatapan MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan dari sebelum Perubahan UUD 1945 sampai dengan penetapan UU No. 12 Tahun 201 I setelah Perubahan UUD 1945. Republik Indonesia Tahun 1945 yang terjadi sebanyak empat kali pada kurun waktu tahun 1999-2002 merupakan c o ns titut i onal reform (The Habiebie Center, 2001:15). yang menjadi acuan bagi dilakukannya reformasi hukum dan ketatangeraan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses reformasi di segala bidang yang terjadi di negeri ini. Perubahan UUD 1945 tersebut telah banyak membawa intplikasi yang cukup mendasar bagi tatanan kenegaraan zu, terutama implikasi terhadap pola hubungan antar lembaga-lembaga negara. Salah satu di antaranya adalah implikasi terhadap reposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari pelaksana seeara penuh kedaulatan rakyat menjadi hanya sebuah lembaga negara dengan kekuasaan yang terbatas sebagai majelis, dan tidak lagi mernpunyai
Sekitar 7 tahun yang lalu pembentuk Undang-undang (DPR dan Pemerintah) mengeluarkan atau tidak memasukan Tap MPR sebagai salah satu jenis dan Hierarkie Peraturan Perundang – undangan di Indonesia dan hal itu sebagai mana tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Dikeluarkannya atau tidak memasukan Tap MPR sebagai salah satu jenis dan Hierarkie Peraturan Perundang–undangan tersebut tidak banyak diperdebatkan meskipun sangat esensial bagi tertip dan kehidupan hukum di Indonesia.
Tap MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki posisi yang setara dengan UU.
Jurnal Abdimas Mandiri
Studi Keberadaan TAP MPR RI Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia Pasca Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2019 •
Studi ini menjelaskan posisi dan kedudukan Ketetapan MPR RI dalam hirarki perundangan di Indonesia yang dilakukan dengan teknik literatur review dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia merupakan produk hukum formil dari lembaga tertinggi negara pra amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi konsekuensi perubahan status Majelis Pemusyarawatan Rakyat Republik Indonesia dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Konsekuensi dari amandem tersebut adalah TAP MPR RI tidak lagi menjadi rujukan pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Perundang-Undangan. Namun setelah direvisi dan ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan implikasi hukum bahwa TAP MPR RI menjadi rujukan bagi peraturan perundangan di bawahnya seperti Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun Peraturan Daerah. Kata kunci: TAP MPR, Undang-Undang, Hukum.
Ketetapan MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan memiliki posisi yang cukup sentral.
RELATED PAPERS
American Behavioral Scientist
When Lockdowns Force "Everyone" to Work From Home: Inequalities in Telework During COVID-19 in Uruguay2023 •
Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam
Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 20242022 •
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
A Semi-Empirical Topographic Correction Model for Multi-Source Satellite Images2018 •
Intensive Care Medicine Experimental
Factors Impact on Insufficient Nutrition and Effects of Timely Adequate Nutrition Support on Patient Outcomes in Adult Intensive Care Patients2015 •
International Journal of Cardiology
Appropriateness criteria for stress echocardiography in patients with acute chest pain: Are we choosing wisely?2013 •
2024 •
Journal of forensic and legal medicine
Cocaine toxicological findings in cases of violent death in Sao Paulo city - Brazil2018 •
Diseases of the Esophagus
P216 What is the Time Burden and Response Rate Associated with Written or Online Completion of Health-Related Quality of Life Questionnaires After Cancer Treatment?2019 •
Ensayo-Gestión del talento humano en la educación peruana
ENSAYO GESTION DE TALENTO HUMANO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS -CLAUDIA GUISILLE YANQUE AGUILAR pdf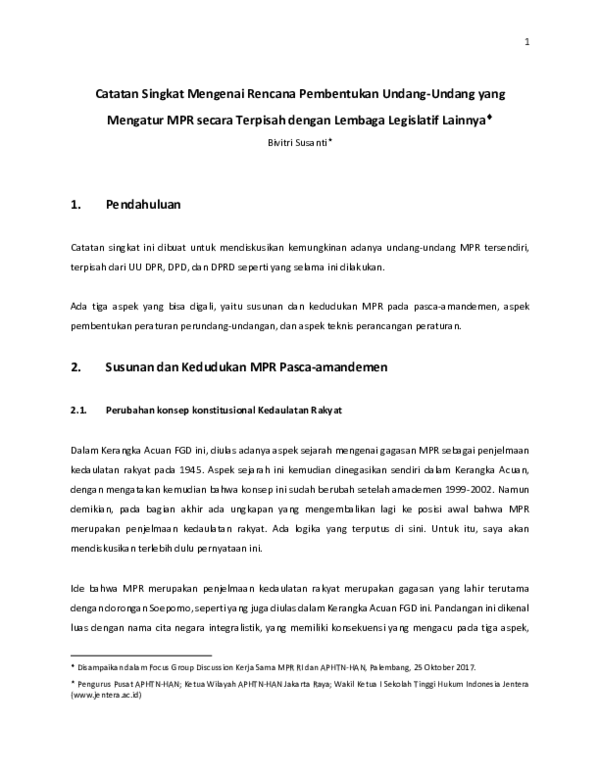
 Bivitri Susanti
Bivitri Susanti